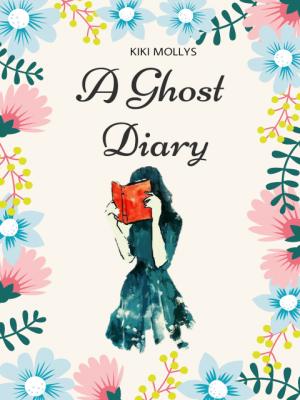Ruang ini kedap suara, tak bisa untuk sekadar bertukar aksara atau bercakap dengan jiwa penuh angkara. Aku sendirian, membiaskan bayang semu dalam gelap membara. Semua terasa sangat tak beraturan. Sakit. Aku merasakan jantung ini keluar dari irama normal. Napasku berat. Jari-jariku saling menggenggam, disertai meremas keras, seakan ingin melepaskannya dari telapak tangan. Kau tahu rasanya sesak memendam perasaan buruk sendirian? Tanpa pasang telinga mana pun yang mendengar, tanpa bahu mana pun yang bisa menjadi tempat bersandar. Aku berseteru sinis dalam hati, merasakan hidupku miris. Menyadari hidup adalah alegoris, terkadang anaforis. Aku tahu, dunia tak hanya sebaris, tetapi berlapis-lapis. Ia anarkis.
Aku merobek satu halaman kertas kesepuluh kalinya saat aku gagal menyampaikan isi kepalaku. Penuh emosi. Ya, selalu penuh emosi. Aku kembali mengencangkan ikatan rambutku yang kini sudah melorot asal. Kaos putih oblong dan celana jeans pendek selutut yang aku kenakan, dan rambutku yang terjuntai amburadul, seolah-olah menggambarkan kondisiku yang sangat berantakan. Aku melepaskan kacamata bacaku yang berbentuk setengah bulat, kemudian mengucek kedua mataku yang telah lelah memelototi buku tanpa hasil apa-apa.
“Adnya yang tidak berguna,” ucapku lantas mengobrak-abrik rambutku yang baru saja kukencangkan ikatannya. Kini, tampilannya malah bertambah tidak karuan.
Ya, namaku Adnya. Adnyana Daniswara. Nama yang diberikan oleh orangtuaku dengan pelafalan yang indah. Nama yang selalu menyertai kebahagiaanku dengan harapan untuk selamanya. Tapi, ternyata harapan itu semu. Ia tidak mengantarkanku sampai detik ini. Prosesku menjadi dewasa layaknya dihujani bongkahan es yang turun secara tiba-tiba. Kaget dan memilukan. Ya, aku hidup sebatang kara sekarang. Sendirian dalam rumah penuh kenangan. Dalam hati aku berteriak pilu. Aku mengepalkan tangan kananku dan memukul-mukul dada kiriku dengan keras, berusaha mengeluarkan sakit yang terpenjara di dalam sana. Menahan rasa sakit sendirian rupanya bukan hal yang baik bagiku, apalagi ditekan oleh dunia dari berbagai sudut, membuatku sangat kalang kabut. Jika dunia menginginkanku tenggelam dan menjadi tidak pantas untuk siapa pun, bahkan untuk diriku sendiri, bolehkah aku menepi sejenak untuk sekadar melihat senjaku di batas langit barat? Berdamai dengan diri sendiri adalah hal yang aku butuhkan saat ini. Biarkan aku tenggelam dalam air mata pasrahku. Aku butuh diriku untuk menyembuhkan lukaku. Pada tangan kecilku, aku menggantungkan sebuah harapan. Harapan kosong yang terus saja kugaungkan.
***
Pamit si malam pada rembulan terekam oleh langit timur. Cahaya sang raja siang masih belum bisa menembus celah-celah kecil sudut kamarku. Berkasnya masih tipis, namun sudah cukup menyadarkan awan untuk kembali terlihat putih setelah gelap mengistirahatkannya. Aku mengerjapkan mataku perlahan. Tidak perlu waktu lama untuk mataku beradaptasi dengan pagi. Aku bangun dengan sisa-sisa air mata yang membasahi bantalku. Tanpa ditebak pun, aku sudah tahu pasti mataku sekarang sebesar buah tomat karena menangis semalaman.
Aku segera duduk, masih di tempat tidur. Tanpa aku sadari, aku kembali menangis. Waktu begitu kejam akhir-akhir ini. Aku mengusap pelan puncak kepalaku sembari memejamkan mata. Kubiarkan saja air mata ini terus keluar. Aku rasa ia jatuh tanpa sia-sia. Aku rasa ia jatuh sebagai perwakilan doa. Dan aku rasa, ia adalah pertanda rindu yang menggebu.
Aku tidak akan pernah lupa usapan lembut jemari ibuku yang setiap pagi membangunkanku. Aku kadang bandel, tidak segera bangun. Aku lebih memilih menutupi seluruh tubuhku dengan selimut dan kembali tidur. Tidak menyerah, ibu kembali mengusap kepalaku yang sudah tertutupi selimut dengan mengucapkan kata-kata lembut, agar aku luluh dan segera bangun. Aku masih ingat deru napasnya yang memburu, tapi hangat. Aku masih ingat aroma wanginya. Aku masih ingat segalanya.
Detik demi detik waktu yang tanpa sadar terlewati kini rasanya seperti hanya mampir. Hampa. Kosong. Gelap. Waktu adalah hal yang tidak bisa diminta dengan sengaja, tidak pula bisa ditolak begitu saja. Apa yang aku harapkan sekarang adalah aku bisa hidup tanpa waktu. Kata orang, waktu bisa menyembuhkan. Apakah itu berlaku untukku juga? Aku tak tahu. Aku tidak ingin menggantungkan apapun kepada waktu. Biarkan ia bergelut dengan dunia ini tanpa melibatkan aku lagi. Sudah cukup.
***
Aku berjalan di sepanjang trotoar. Suara bising klakson kendaraan menjadi latar suara yang selalu menemani setiap pagiku. Bukannya aku suka, hanya saja aku sudah terbiasa. Segala bising yang masuk ke dalam telingaku, kini aku anggap seperti suara anak kucing yang menggemaskan. Lagi, bukan karena aku suka, melainkan karena sudah terlalu muak dengan suara-suara asing yang memekakkan telinga. Aku sengaja melambatkan langkah kakiku agar tidak segera sampai di tempat tujuanku saat ini. Ya, sekolah. Aku benci sekolah akhir-akhir ini. Aku pikir sekolah adalah sumber dari segala kebisingan yang memaksaku untuk mendengarkannya.
Aku melewati beberapa pedagang yang berjualan di bahu jalan. Sesekali aku berhenti di salah satu pedagang langgananku tiap pagi yang menjajakan makanan-makanan ringan dan air mineral. Bapak itu bernama Pak Sugeng. Aku sengaja berhenti dan berbincang agak lama untuk ikut bersenda gurau dengannya –dan dengan pedagang-pedagang di sebelahnya, dan tentunya untuk mengulur waktuku tiba di sekolah. Pak Sugeng sudah hapal denganku karena setiap pagi aku mampir ke lapaknya.
“Neng Adnya ini kebiasaan. Sudah hampir jam 7 kok masih nongkrong di sini? Nggak takut telat, Neng?” Tanyanya.
“Saya malah pengen telat, Pak. Kalo bisa pengen dihukum hormat ke tiang bendera berjam-jam,” jawabku sembari memeragakan gaya hormat ke bendera, disusul dengan gelak tawa si bapak.
“Saya dulu bandel, Neng. Suka bolos jam pelajaran pas masih SMP dan saya nyesel sekarang,” celetuk si bapak. Aku terdiam sejenak. Lalu si bapak melanjutkan, “lebih baik Neng Adnya sekarang berangkat ke sekolah ya, Neng. Bapak nggak mau Neng Cantik bandel.” Si bapak menjeda omongannya karena sedang meladeni seorang pembeli.
“Kadang apa yang disukai itu belum tentu baik, dan apa yang nggak disukai itu justru yang baik. Semua hanya nunggu waktu aja, Neng.” Aku tersenyum kikuk dan mengangguk. Lalu aku memutuskan untuk berpamitan dengan si bapak dan melanjutkan perjalanan ke sekolahku yang tinggal lima menit lagi pasti gerbang sekolah akan ditutup.
Aku menghembuskan napas panjang. Terlalu lelah memikirkan apa yang seharusnya tidak aku pikirkan, menelaah kata-kata di sekelilingku yang menohok ulu hatiku, dan memikirkan bahwa tidak hanya semesta yang mengajakku berdamai, namun juga seluruh isinya. Tapi di lain sisi, aku masih ingin menyangkal itu semua. Aku masih benci sekolah.
***


 ditalungit
ditalungit