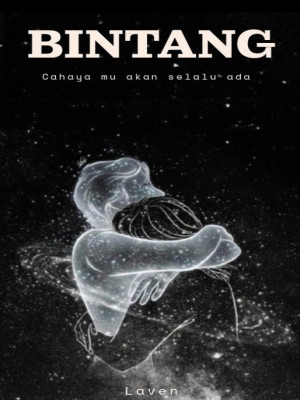.
.
.
Adiksi © Fukuyama12
Diary 19 Ketakutan yang Menghampiri
Nofap hari ke-68
.
.
.
Ruangan bercat putih itu terasa sangat dingin dan menusuk tulang. Aku yakin meski pendingin ruangan tidak dinyalakan, aku akan tetap merasa kedinginan. Namun, entah mengapa keringat terus menetes di kulitku. Aku duduk pada kursi yang ada di depan pembimbing BK dengan kegugupan yang memenuhi leherku.
Wanita berumur hampir lima puluh tahun itu menaikkan kacamatanya, matanya menyipit saat menatap wajahku, lalu beralih pada kertas berisi daftar absensi.
“Mas Ghazi, ya?” tanya Bu Laili.
Aku mengangguk kaku. Aku pastinys sudah terlihat seperti robot sekarang. “I–iya, Bu.”
“Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini?”
Suaranya yang tegas itu terdengar lebih menyeramkan daripada musik latar di film-film horor.
“Tidak tahu, Bu.”
Tatapan sinis yang diterima olehku sejak pagi tadi itu berpindah pada abu Laili yang hanya berjarak sekitar lima puluh senti di depanku. Aku jadi menciut dibuatnya, belum lagi pertanyaan yang memusingkan itu.
Helaan napas terdengar kasar. “Ibu dapat laporan dari salah satu murid di sini.” Tangannya yang keriput itu mengulurkan ponsel yang menyala dan menaruhnya di depanku. Lalu memutar sebuah rekaman.
Aku sudah merasa jika sesuatu yang buruk akan terjadi, terlebih saat melihat rekaman itu. Video yang ditampilkan sangat tidak jelas, bahkan tidak berfokus pada satu objek, lebih seperti rekaman buram. Hanya saja, suara yang keluar dari video itu sudah cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi.
‘Apa? Oh, kamu takut? Iya, aku di sini untuk menemanimu, kok! Bagaimana jika ikut dengan ke suatu tempat? Mau tidak ikut denganku? Nanti aku kasih bayaran, deh. Bagaimana? Kau mau berapa? Biru atau merah?’
Pupilku mengecil saat mendengarnya. Meski agak berubah, aku—dan pastinya wanita di depanku ini—tahu jika suara itu seperti milikku. Mungkin itu hanya kebetulan saja, tetapi kalimat yang mengalir masuk ke dalam telingaku berhasil memutar kembali kejadian yang terjadi beberapa bulan yang lalu, ingatan itu berputar dengan sangat jelas, lebih jelas dari video yang sedang kulihat.
‘Berhenti mengganggu! Jika kau melangkah lagi, akan ku laporkan ke polisi!’
Napasku tertahan. Aku kembali teringat dengan suara gadis yang kuganggu malam itu. Gambar video itu berganti, menunjukkan seorang pemuda yang menutup wajahnya saat sinar kamera menyenternya.
Postur tubuh itu, pakaian hitam dengan corak tribal berwarna biru neon, dan topi bisbol yang hanya dijual di toko tertentu saja. Semua itu seperti milikku yang saat ini sedang tersimpan rapi di dalam lemari. Itu jelas bukan kebetulan.
"Apa ini kamu?"
Kerongkonganku tercekat. Mulutku terbuka tetapi aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, seakan ada batu besar yang menghalangi. Aku menunduk dan menatap jari-jari yang terasa dingin dan bergetar. Aku ingin mengelak, ingin rasanya berkata 'bukan' dan 'itu pasti orang lain'. Namun, Aku tidak bisa, aku bahkan lupa rasanya untuk bernapas, yang keluar dari tubuhku hanya tetesan-tetesan keringat dari kulitnya.
Guru Pembimbing itu mengeluarkan secarik kertas bergambarkan sebuah foto yang diambil dengan kamera ponsel. Ada tanggal yang tertera di sana, dan itu terjadi dua hari yang lalu. Hanya saja, aku lebih fokus pada objek yang menjadi fokusnya, yaitu tas jingga bermotif mapel yang menggantung digantungan yang berada di belakang pintu. Sekali lagi, itu mirip dengan pintu kamarku.
Gambar di bawahnya adalah foto buku yang dikeluarkan dari tas yang bahkan belum pernah kubuka sekali pun. Di sana, tertulis sebuah nama, 'Sofia Andhira Ambarningsih', nama asing yang belum pernah kudengar dan kubaca sebelumnya.
"Dia bilang ini diambil di kamarmu. Apa benar kamu menyimpan tasnya?"
Aku diam membisu, seperti patung anak kecil yang ada di kolam sekolah. Tenggorokan dan bibirku sama-sama terasa kering. Apa benar aku bisa berbohong di saat-saat seperti ini? Tetapi bayangan senyuman Ibu yang akan berubah menjadi tangisan membuat hatiku terguncang. Bagaimana marahnya ayah saat mendengar aku yang hampir saja memperkosa seorang gadis. Belum lagi ketiga temanku—Kak Afkar, Kak Fayruz, dan Kak Fayra—yang sudah susah payah kudapatkan. Juga, orang-orang yang ada di sekitarku, apakah mereka akan menatapku lebih sinis dari yang aku dapatkan hari ini?
Di mana aku harus memasang muka nanti setelah keluar dari ruangan dingin ini?
“Itu … itu …” Suaraku bergetar, sama seperti tubuhku. Pandanganku jadi tidak bisa fokus pada satu arah saja. Kebimbangan yang muncul di hati ini terasa menyakitkan.
Seperti kesal karena aku tidak kunjung menjawab, Bu Laili kembali menunjukkan sebuah lembaran lain. Mataku melebar saat melihatnya. Di sana, terpampang foto seorang gadis berambut panjang yang dikucir satu. Di punggungnya, terdapat tas yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Bu Laili, dan tas yang sama dengan yang ada di kamarku. Namun, yang membuatku kembali terkejut adalah wajah gadis itu. Benar. Tidak salah lagi. Bayangan wajah samar yang ada dalam ingatanku menjadi jelas.
Gadis ini ….
“Kalau kamu jujur semua akan jadi lebih mudah.”
Nasihat yang kudapatkan tidak membuatku menjadi lebih baik. Lagi pula semua tatapan itu pasti tidak akan hilang meski aku berkata jujur, kan? Namun aku tahu jika dengan berbohong semua tidak akan berubah menjadi lebih baik.
Aku tahu itu.
Sudah bertahun-tahun aku berbohong kepada kedua orang tuaku, tentang kegiatan yang biasa kulakukan di malam hari hingga mengacaukan hidupku. Aku juga sudah berkali-kali berbohong pada diriku sendiri. Setelah melakukan hal itu, aku pasti akan berkata pada diriku sendiri jika 'ini yang terakhir, aku tidak akan mengulanginya lagi', tetapi nyatanya aku terus melakukannya sampai insiden malam itu terjadi. Aku berbohong dan berkata ‘Tidak apa-apa, toh ini hal yang biasa bagi laki-laki’, padahal apa yang ia lakukan bukaan hal biasa, masturbasi setiap malam bukan hal yang normal dan di luar batas.
Dan semua kebohongan itu berujung pada penyesalan seumur hidup, apalagi jika berkaitan dengan hal seperti yang satu ini. Mungkin aku bisa gila jika harus menanggung beban setelah berbohong dan mengatakan jika bahwa yang ada di sana itu bukan dirinya.
“Ghazi?” Panggilan yang biasa kudengar dari orang asing itu membuatku mengangkat kepala. “Tidak apa-apa, coba cerita saja dulu.”
Kata-kata yang lembut itu tidak sama dengan wajah kaku yang menatapku. Bagaimana bisa aku bercerita di saat-saat seperti ini? Otak dan mulutku pun sudah tidak bisa diajak kerja sama.
“Itu .…” Aku menahan napas.
Tiba-tiba saja pandanganku mengabur, lalu aku merasakan tetesan air menetes dari sudut mata, mengalir melewati pipi—yang sudah mulai tidak berjerawat, dan jatuh di atas celana abu-abu yang sedang kupakai. Semakin lama semakin deras, seakan aku sudah tidak bisa menahan bendungan itu. Beban yang bahkan belum aku angkat itu sudah terasa sangat berat.
Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa sakit dari bibir yang kugigit hingga berdarah tidak terasa menyakitkan.
“Itu … benar, itu saya. Maaf, saya tidak bermaksud untuk melakukan itu.” Aku mengangkat wajah yang basah dengan air mata dan menatap mata yang da di depanku. “Tapi saya bersumpah tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Saya … saya berhenti di situ saja! Lalu—”
“Ghazi.”
Panggilan yang menusuk itu membuat seluruh kata-kata yang sudah tersimpan rapi dalam otakku runtuh seketika dan aku kembali lupa bagaimana caranya bernapas.
“Simpan cerita itu untuk nanti.”
Wanita itu menoleh pada guru pembimbing konseling yang lain, yang ikut mendengarkan pembicaraan tertutup kami. “Tolong panggil orang tua Ghazi ke sini.”
Semua bayangan yang aku pikirkan tadi kembali masuk ke dalam benakku. Hancur sudah masa depanku, senyuman orang tuaku, dan harga diriku. Aku tidak bisa menghentikan jemari keriput yang mulai mencari nomor telepon orang tuaku dalam daftar siswa sekolah ini. Aku terlalu sibuk memikirkan nasib selanjutnya.
Aku diam saja di tempat dudukku, seolah ad
a lem yang melekat di sana. Aku hanya bernapas dengan pelan dan diam-diam terus meneteskan air mata, biar saja aku dianggap cengeng, aku sudah tidak peduli lagi jika wajah ini tercoreng. Berharap agar bisa menghilang seperti abu pun adalah hal yang bodoh dan tidak mungkin terjadi. Jadi, aku memutuskan untuk diam dan mempersiapkan hati untuk apa yang akan terjadi ke depannya.
Sampai kedua orang tuaku datang, tidak ada perbincangan yang terjadi di antara kami. Bahkan kedua guru itu tidak berkeinginan untuk menghentikan tangisanku. Mereka bahkan tidak memberiku minum demi menghilangkan rasa dahaga di tenggorokanku.
Suara ketukan itu terdengar sangat menyeramkan. Aku menebak-nebak siapa yang akan memasuki ruangan ini. Dan benar saja, dua orang yang berbagi kasih sayang denganku ada di sana, berdiri dengan wajah khawatir, terutama setelah melihat tangisan anak satu-satunya.
Namun, wajah Ayah yang mengeras cukup untuk membuatku gemetar ketakutan. Langkah kakinya yang tegas dan suara sepatu yang berbenturan dengan lantai putih itu membuatku berdiri panik. Mataku melebar, lalu menutup dengan cepat bersamaan dengan tangan yang terangkat tinggi-tinggi.
"Ayah!"
Sayangnya, panggilan keras Ibu tidak cukup untuk menghentikan tangan yang mengayun cepat dan mendarat di pipiku.


 fukuyama12
fukuyama12