Selama berjam-jam mobil-mobil berseliweran di jalanan. Entah mencari apa. Mungkin berlomba mengejar waktu. Aku menghembuskan napas berat di trotoar yang aku lewati. Kelabu. Warna langit senja tak semerah biasanya. Dasar mendung sialan!
Kulirik arlojiku. Pukul 17.30. Aku harus pulang. Berjam-jam meninggalkan rumah rasanya membuatku rindu—meskipun aku tahu, tidak akan ada yang menyambutku nantinya.
‘Beep’
Ponselku berbunyi. Aku pun mengambilnya dari dalam saku seragamku. Ada panggilan masuk dari Eka, teman sekelasku.
“Halo?” sapaku.
“Lidya, kamu di mana?” Suara Eka terdengar panik di seberang sana.
“Di Jalan Koral Emas. Lagi mau pulang. Kenapa?”
“Ratni, Lid!”
“Ratni kenapa?”
“Ratni hilang!”
Aku sampai tersedak salivaku sendiri begitu mendengar kabar itu. Ratni menghilang? Gadis pendiam itu? Siapa yang menculiknya?
“Sejak kapan? Memangnya sudah dicari?” tanyaku.
“Sejak pulang sekolah tadi, Lid. Sudah. Aku sudah mencari di rumahnya, bahkan seluruh teman sekelasmu sudah kutanyai. Tapi nggak ada yang tahu di mana dia.”
“Kamu sudah menghubungi nomor teleponnya?”
“Sudah. Aku sampai stress menghubunginya. Ponselnya nggak aktif!”
“Sudah lapor polisi?”
“Belum....” Suara Eka terdengar ragu.
“Kalau memang belum ketemu di segala tempat, sebaiknya kamu lapor polisi dulu.”
“Aku takut, Lid.”
“Takut kenapa? Aku temenin, deh.”
Eka tidak menjawab. Lama sekali. Akhirnya ia berkata dengan suara bergetar di seberang sana, “Iya deh, b-besok ya, kalau sampai malam nanti Ratni gak ada kabar. Aku akan minta surat dispen dari sekolah.”
‘Tuuuut’
Panggilan ditutup. Aku menurunkan ponsel dari telingaku. Ratni menghilang dan Eka bersikap aneh. Aku menghela napas lagi. Wajar kalau Eka mengkhawatirkan Ratni. Mereka adalah sahabat sejak kecil. Ratni adalah anak yatim-piatu. Orangtuanya meninggal semenjak ia SMP. Ia kini tinggal sendirian. Yah, semoga tidak terjadi apa-apa.
“Yo!”
Aku menoleh pada pemuda berkulit pucat yang memberi sapaan padaku. Ia bersandar pada dinding sebuah bangunan. Tubuhnya yang tinggi besar serta pakaiannya yang serbahitam membuatnya terlihat seperti tiang lampu berjalan ketika ia menghampiriku.
“Aku mau pulang,” ucapku dengan suara lirih.
“Tugasmu belum selesai. Lagipula, untuk apa kamu berjalan ke sini?” tanyanya.
“Menunggu taksi lewat,” jawabku sekenanya. Aku mengalihkan pandangan dari mata hitamnya yang menatapku tajam, seolah ada sesuatu dariku yang tak akan ia biarkan lolos begitu saja. Asal kalian tahu, pemuda ini bisa sedikit menyeramkan bila ia sudah memberikan tatapan seperti itu.
Aku melambai pada taksi yang hendak lewat. Ia segera menarik tanganku dan menggeleng pada sopir taksi yang hampir saja berhenti di depan kami. Aku menatapnya marah. Kusentakkan tanganku darinya dengan keras.
“Apa-apaan sih, kamu, Fino?” bentakku. Ah ya, namanya Fino. Alfino Hendramarto, kalau kalian ingin tahu. Ia teman satu sekolahku. Tapi kami berada di kelas yang berbeda. Tentang bagaimana aku mengenalnya, mungkin itu karena kami memilki kesamaan. Yah, kami sama-sama terikat dalam janji tak masuk akal yang dibuat oleh seorang manusia sinting.
“Jujur saja, Lidya. Teman sekelasmu hilang, kan?” tanyanya. Matanya menyipit. Suaranya dipelankan, namun terdengar mengancam.
“Iya,” jawabku cepat-cepat sembari membuang muka.
“Dan kamu berniat mencarinya di sini, bukan?”
Enggan rasanya menjawab. Tapi aku tetap mengangguk dan berkata, “Ya.”
“Kamu memang benar.”
Aku kembali menatapnya. Sosok Fino yang tinggi besar membuatku harus mendongak untuk bisa memandang sorot matanya yang penuh kejujuran. Mataku membulat tak percaya. “Ratni ... ada di sini? Bersamamu?”
Fino mengangguk.
Awalnya, aku tersenyum bahagia. Aku hampir menghubungi Eka ketika tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Kembali kumasukkan ponselku di dalam saku seragamku. Senyumku surut. Kutatap Fino penuh waspada. “Seperti apa keadaannya?”
Ujung bibir Fino tertarik ke atas, membentuk sebuah senyum miring yang terkesan tidak ramah. “Kamu tahu sendiri seperti apa keadaannya.”
***
Kami berjalan melewati gang-gang sempit. Penerangan di area ini sangat minim. Bau busuk dari sampah yang berserakan membuat mataku berair. Aku mengambil saputangan dari dalam tas ranselku dan menutupi hidungku. Di tempat ini, tikus dan kucing liar bebas berkeliaran. Aku hampir saja berteriak ketika segerombolan tikus merayap di bawah kakiku. Fino menertawai sikapku. Seekor kucing liar menggeram marah ketika aku mencoba menyentuhnya. Aku mendapat hadiah luka cakar di tanganku sebagai akibat dari tindakanku itu.
Di tempat ini, segala sesuatu bisa saja terjadi. Perdagangan narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, segala yang tak tampak di dunia luar akan tampak di area ini ketika malam tiba. Jalan Koral Emas memang dikenal sebagai jalan yang berbahaya. Dan gang-gang sempit ini adalah bagian dari kegelapan yang disuguhkan area ini pada kami. Fino sengaja membawaku melewati beberapa jalur yang rumit untuk menghindarkan kami dari segala kemungkinan buruk yang terjadi. Kepalaku terasa berputar-putar. Selama setengah jam kami berjalan, tempat yang dituju tidak juga nampak. Melewati gang-gang sempit ini rasanya seperti melewati labirin tanpa akhir.
“Berapa lama lagi kita....” Aku bertanya di tengah rasa lelahku. Aku ingin sekali bersin dan muntah.“Sst, diamlah!” bisik Fino. Ia berhenti melangkah, lalu membekap mulutku yang hendak mengeluarkan pertanyaan lagi. Untung ada saputangan yang menghalangi kontak antara tangannya dan bibirku secara langsung.
Aku mendengar suara tertawaan beberapa orang pria dewasa, serta desahan seorang wanita. Sepertinya suara itu berasal dari sudut gang yang hendak kami lewati
“Kita harus melewati jalan lain.”
Aku mengangguk. Fino melepaskan tangannya dariku. Kami pun mengambil jalan memutar sembari menjaga langkah agar tidak terdengar oleh orang-orang di gang itu. Aku mencengkeram lengan pakaian Fino. Fino tidak bergeming. Ia tetap diam sembari memasang tatapan waspada. Aku masih menutup hidung dan mulutku dengan saputangan, namun kali ini lebih rapat karena bau di area ini lebih busuk dari gang sebelumnya. Sialan! Kapan neraka menjijikkan ini akan berakhir?
“Demi Ratni,” gumamku.
Aku kembali mendongak menatap Fino. Kudapati bibirnya kembali tersenyum miring setelah nama ‘Ratni’ disebut. Namun matanya memancarkan kesedihan. Mungkin ia merasa miris. Aku kini menunduk. Seolah ada sesuatu yang hilang dariku, aku kembali merasakan kekosongan dalam diriku. Air mataku menetes. Bahkan sebelum Eka mengabariku sore tadi, aku sudah tahu bagaimana keadaan Ratni yang sebenarnya.
***
Rumah mungil berdinding batu itu akhirnya menampakkan wujudnya setelah sekian lama kami mencarinya. Butuh perjuangan selama satu jam lebih sepuluh menit untuk sekedar menemukannya. Gang-gang sempit itu memang benar-benar neraka! Melewatinya saja sudah membuatku pusing. Aku melepas saputangan dari mulutku dan mengeluarkan segala isi perutku di dekat tong sampah. Setidaknya udara di tempat ini sedikit lebih baik. Tidak ada aroma daging busuk atau sisa-sisa hasil pencernaan seperti yang kudapati di gang-gang sebelumnya.
“Maaf,” ucapku begitu Fino menekan leherku untuk membantu mengeluarkan segala isi perutku.
“Tidak apa-apa. Aku juga begitu sejak pertama kali berkunjung ke tempat ini.” Fino melepas tangannya dari leherku ketika aku menegakkan badan. “Tapi, apa kamu yakin akan memasuki bangunan ini? Kondisinya bisa lebih parah dari gang-gang itu.”
Aku menggeleng. “Tidak apa-apa.”
Fino menempelkan jarinya pada sensor di dinding rumah itu. Pintu merahnya pun terbuka. Fino mengisyaratkanku untuk mengikutinya. Aku menurut. Pintu menutup secara otomatis setelah kami masuk. Hanya ada satu lampu kecil yang menjadi penerang di ruangan yang kini kami masuki. Fino berjalan menuruni tangga yang mengarah pada ruangan bawah tanah. Aku cepat-cepat mengikutinya.
Ruangan di bawah tangga sangat gelap. Fino segera meraih tanganku ketika aku tengah meraba di dalam kegelapan. Terdengar suara pintu lain yang terbuka. Tak lama kemudian, sebuah cahaya menerangi kami. Fino menarikku memasuki ruangan di balik pintu itu. Kemudian, pintu di belakangku pun tertutup dengan suara keras.
Aku mengucek-ucek mataku untuk menyesuaikan diri dengan cahaya di ruangan ini. Sebenarnya, ruangan ini sendiri tidak cukup terang. Hanya terdapat beberapa lampu yang menyala remang-remang. Jumlahnya tidak sepadan dengan luasnya ruangan ini. Ada beberapa tabung seperti akuarium raksasa yang berjejer di sisi ruangan. Aku mungkin tidak perlu terkejut begitu mengetahui apa isinya, karena aku sudah pernah melihatnya sebelumnya. Manusia. Tubuh-tubuh manusia tak bernyawa mengisi masing-masing tabung itu.
Aku tidak perlu terkejut. Sumpah. Bahkan ketika aku melihat seorang dokter sinting tengah mendorong kursi roda berisi Ratni yang terikat di atasnya, seharusnya aku tidak perlu terkejut. Aku pernah berada di sini sebelumnya. Aku pernah membantu dokter sinting itu membelah perut para mayat yang mengisi tabung-tabung itu.
Ratni meronta di atas kursi roda. Wajahnya basah oleh air mata. Ia memohon kepadaku. Mulutnya bergumam tak jelas karena diplester oleh lakban.
Kasihan Ratni. Dia adalah teman terdekatku di sekolah selain Eka dan Tiara. Meskipun pendiam, dia adalah sumber contekan yang baik dan teman yang dapat dimanfaatkan. Aku juga sama sepertinya, sama-sama tidak memiliki orang tua. Kadang kami saling bertaruh seberapa sabar dan tabahnya kami menjalani kehidupan sekeras itu. Tapi sekarang, tidak lagi.
Nyatanya aku lebih beruntung dari Ratni. Dan nyatanya, kami berbeda, sangat jauh. Ratni adalah korban, sedangkan aku adalah pelakunya. Seharusnya aku tidak perlu terkejut ketika mendengar Ratni menghilang, karena justru akulah yang menculiknya. Seharusnya aku tidak perlu berpura-pura menjadi gadis baik yang mengkhawatirkan keadaan teman senasibnya. Dan seharusnya, aku menampakkan ekspresi yang sama dengan Fino.
Ya, akulah orang jahat itu.
Tetapi, bukan aku satu-satunya. Dokter sinting itulah dalang dari semua ini. Guru Ekonomi yang kini berdiri di dekatnya itu adalah anak buahnya yang pertama. Lalu Fino, anaknya sendiri, adalah anak buahnya yang nomor dua. Sedangkan aku, orang yang mengikat perjanjian tak masuk akal dengannya, adalah anak buah terakhir, nomor tiga.
Si dokter gila mengkoordinasi kami semua untuk bersama-sama terlibat dalam penelitian sintingnya. Ia berpendapat bahwa manusia yang sekarang sudah terlalu bodoh untuk bertahan hidup di dunia yang beradda di ambang kehancuran ini. Maka dari itu, ia ingin membuat manusia baru dengan akal pikiran yang lebih sehat. Dokter gila mulai menculik orang-orang yang hidup sebatang kara. Namun ia enggan membunuh orang yang sudah tua. Manusia baru yang ia ciptakan nantinya harus memiliki tubuh yang segar bugar. Maka, ia pun memerintahkan kami untuk menculik para remaja dan anak-anak yang yatim-piatu untuk dijadikan bahan penelitiannya. Bahkan tak jarang ia menyuruh kami untuk menculik mahasiswa atau orang dewasa dengan kisaran umur 20 sampai 30 tahun untuk dijadikan kelinci percobaan.
Tubuh para korban akan dibelah, lalu diambil seluruh organ dalamnya. Tubuh-tubuh itu kemudian disimpan di tabung-tabung raksasa berisi cairan pengawet. Kelak, si dokter gila, dokter sinting, atau apapun julukannya ini akan mengganti organ dalam mereka dengan mesin yang lebih berguna. Tak hanya itu, ia juga akan menukar otak mereka dengan sebuah mesin yang bisa melakukan apa saja.
Ide yang sangat gila, bukan?
Namun, sampai sekarang dokter gila belum juga mengembangkan penelitiannya. Ia masih sibuk mengumpulkan tubuh korban hingga mencapai jumlah yang sudah ia tentukan. Anak buah pertama alias Bu Nadira si guru Ekonomi mata duitan bertugas membantunya menjual organ dalam dari para korban ke pasar gelap. Aku dan Fino bertugas untuk mencari calon korban.
Dari sinilah aku dapat hidup dan memenuhi segala kebutuhanku. Buruk? Ya, sangat buruk dan kotor. Namun beginilah caraku hidup. Di kota X, semua bisa dilakukan untuk bertahan hidup. Bahkan cara sekotor apapun halal dilakukan asal tidak diketahui oleh pihak berwenang. Semua itu sudah menjadi rahasia umum di kota ini.
“Lidya, Fino, bantu kami membedah tubuh gadis ini, ya!” ucap Bu Nadira, guru Ekonomi gila harta yang menjadi rekan kerja kami. Suaranya bergema dengan nyaring di ruangan ini.
Aku dan Fino mengangguk. Ratni melotot padaku sembari berteriak. Aku memberinya senyuman miring seperti yang dilakukan Fino. Dasar gadis polos! Sebentar lagi tubuhnya akan bergabung bersama mayat-mayat di tabung itu.
Aku segera memakai sarung tangan, masker, dan mengambil pisau bedah. Fino melakukan hal yang sama. Si dokter sinting mendorong kursi roda Ratni ke ranjang bedah. Ratni berteriak kencang. Ia meronta semakin keras. Namun si dokter sinting bersama Bu Nadira tertawa lepas. Aku dan Fino saling pandang, lalu saling melempar senyum sarkatik. Sesaat kemudian, air mata menetes dari kedua mata Fino. Begitu juga denganku.
***
Darah. Seluruh pandanganku dibutakan oleh warna merah yang busuk itu. Aku mendengar keduanya menjerit kesakitan. Namun aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya dapat memanggil nama mereka dalam diam, tanpa tahu apa yang harus aku lakukan.
Sesaat kemudian, semuanya berubah. Rumahku berantakan. Kaca jendelaku pecah dan serpihan-serpihannya berserakan di bawah kakiku. Meja dan sofa masih pada tempatnya, namun entah sejak kapan terdapat sobekan memanjang di setiap sisinya. Meja mahal milik keluarga kami rusak, sudah tak karuan bentuknya. Darah bercipratan di segala tempat, membasahi dinding, perabotan, dan lantai. Bau anyir menyeruak, membuatku hampir muntah!
Saat itulah tangan itu terulur padaku. Aku masih ingat bagaimana penampilannya saat itu. Jas putihnya bersih tanpa noda. Dengan senyum simpatiknya serta mata hitamnya yang teduh itu, ia berkata padaku, “Bisakah aku menolongmu?”
Dengan bodohnya, aku mengangguk. Aku terikat dalam janji aneh itu. Janji yang amat mustahil. Si dokter sinting telah menipuku dan menarikku masuk ke dalam dunianya yang juga sinting. Sekali masuk, aku tidak akan bisa keluar. Nyawaku taruhannya.
“Kamu akan menyukai ini, Lidya. Inilah yang dinamakan hidup. Hahahahahaha!”
Dengan santainya, ia membedah perut seorang gadis yang masih dalam keadaan sadar. Aku mengenali gadis itu sebagai penghuni panti asuhan di dekat sekolahku. Teriakannya menggema di seluruh ruangan. Begitu menyayat hati. Isakan tangisnya mengigatkan diriku ketika mereka pergi. Aku sama seperti gadis itu. Namun aku lebih beruntung, setidaknya.
“Lidya, coba lakukan!” Si dokter sinting menyerahkan pisau bedah padaku. Si gadis masih dalam keadaan setengah sadar. Luar biasa. Tapi miris. Seharusnya ia menyerah saja. Semua rasa sakit itu akan menghilang bila ia mati saat itu juga. Tapi ia masih bernapas. Dari sorot matanya, aku menangkap keinginan untuk terus hidup.
Tanganku gemetar begitu menerima pisau bedah yang bersimbah darah itu. Aku menatap gadis itu sekali lagi. Tatapannya terlihat mengiba padaku. Isakannya terdengar lemah. Aku memalingkan wajah darinya sembari menahan tangis.
“Kamu tidak tahu cara melakukannya?” bisik si dokter sinting. Aku begidik mendengarnya.
Aku menggeleng dengan ragu. Dengan suara yang nyaris mencicit, aku berkata, “Saya tidak tahu, Dokter.”
“Begini,” Si dokter sinting mengambil pisau bedah dari tanganku, ia mengarahkan pisau itu pada dada kiri si gadis, namun tidak sampai menyentuhnya. “Kau tinggal menancapkannya dengan garis lurus vertikal, lalu putar pisaumu dan selesai. Paham?”
Aku mengangguk.
Si dokter sinting kembali menyerahkan pisau itu padaku. Aku menggenggam gagang pisau dengan erat. Aku mendekati gadis itu. Kuabaikan tatapan mengibanya itu.
“Maaf,” desisku, sebelum pisau yang kubawa menancap dengan tepat di dada kirinya.
Ia menjerit dengan keras. Aku memutar pisau itu. Darah menyembur keluar dari dadannya, membasahi pakaian dan wajahku. Ia berteriak semakin keras. Namun beberapa detik kemudian, teriakannya surut. Ia tidak lagi bersuara. Kepalanya tergolek lemas di sisi ranjang. Matanya masih melotot, memancarkan rasa sakit tak terkira yang ia rasakan sebelumnya. Gadis itu sudah tidak bernyawa. Aku ... telah membunuhnya.
Kedua kakiku lemas dan aku terduduk di lantai dengan pandangan kosong. Di saat seperti itu, bisa-bisanya si dokter sinting bertepuk tangan sembari tertawa.
“Bagus, bagus, anak pintar!” pujinya sembari mengelus puncak kepalaku.
Aku tidak tahu harus memberi tanggapan seperti apa terhadap pujian itu. Aku ingin menangis. Aku ingin menjerit. Aku ingin muntah. Namun aku juga ingin tertawa. Aku tidak tahu perasaan campur aduk apa yang merasuki jiwaku. Apakah begini rasanya ketika baru saja membunuh seseorang?
“Kamu berbakat, Nak! Kamu tidak seperti anakku yang penakut itu. Lihat! Dia hanya bisa duduk diam di sana sembari memandang kita!”
Aku menoleh pada Fino yang membelalak padaku di sudut ruangan. Ketika aku menatapnya, wajah pucatnya semakin terlihat pucat. Seingatku, aku masih berusia 12 tahun saat itu. Usia yang masih terlalu belia untuk mengetahui kejamnya dunia. Kurasa saat itu Fino mulai membenciku. Namun aku tidak dapat membencinya.
Aku menangis, tapi juga tertawa. Si dokter sinting tertawa bersamaku. Fino terisak. Namun dokter sinting mengabaikannya, begitu juga denganku. Pada hari itu, sesuatu yang bernama ‘kewarasan’ telah direnggut dariku.
***
Sekali lagi. Tidak. Mungkin harus berkali-kali lagi. Ya, mungkin aku harus menyaksikan organ yang terburai dari perut korban bedah si dokter sinting seperti saat ini. Organ-organ itu kini tengah dipreteli satu per satu oleh Bu Nadira, si anak buah pertama yang juga sinting.
Aku memandang jasad yang tergeletak di ranjang bedah itu untuk terakhir kalinya. Ya, terakhir kalinya. Jasad Cecil, temanku sewaktu TK. Bisa dibilang, ia adalah teman pertamaku. Ketika semua anak menjauh dariku karena aku dinilai terlalu cengeng, Cecil adalah orang pertama yang mengulurkan tangan padaku, mengajakku bermain.
Gadis yang malang. Padahal ia baru saja kehilangan kedua orang tuanya karena sebuah kecelakaan pasawat terbang. Sekarang ia harus menyusul mereka ‘berpulang’. Cecil yang ceria sekarang hanyalah seonggok daging tak bernyawa yang telah diambil organ dalamnya. Nantinya, organ-organ itu akan dijual ke pasar gelap oleh Bu Nadira yang sinting dan menambah pundi-pundi kekayaannya.
Cecil, maafkan aku.
Tapi tidak ada kata maaf.
Mungkin sudah terlambat.
Karena akulah orang jahat yang telah membunuhnya. Hahaha....
Mungkin Cecil tengah mengutukku sekarang. Aku masih bisa merasakan kebencian di wajahnya yang tak bernyawa. Matanya melotot, pandangannya tertuju ke arahku. Namun aku yang berdiri di sini justru meledeknya dengan senyum sinis. Dan tololnya, aku menganggap apa yang telah kulakukan sebagai hal yang wajar. Aku melakukan semua hal kejam ini untuk bertahan hidup. Dan itu manusiawi.
“Jangan diam saja,” bentak Fino.
Aku menoleh padannya, mendengus kesal. Aku tidak mengerti apa yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Tapi ia tidak seperti Fino yang kukenal. Fino adalah sosok yang pendiam dan sedikit lemah di balik sosok luarnya yang tampak kuat. Ia lebih sering menangis bersamaku daripada membentakku seperti sekarang dan pagi tadi.
“Cepat kerja!” bentaknya lagi.
Aku masih tak bergerak. Fino memalingkan wajahnya padaku sembari menggerutu. Ia memejamkan mata, lalu tangannya bergerak memindahkan gumpalan usus yang masih berselimut darah ke dalam wadah berisi cairan pengawet. Dia tengah memaksakan diri, tentu saja. Melihatnya membuatku prihatin.
Lagipula, pekerjaanku sudah selesai. Aku sudah membantu si dokter sinting membunuh Cecil—tentu aku yang bersikeras membunuh Cecil terlebih dahulu karena sebelumnya si dokter sinting berniat membedahnya hidup-hidup. Obat bius yang diberikan Fino ternyata hanya untuk melumpuhkan Cecil saja. Dasar bodoh! Seharusnya ia memberikan obat yang dosisnya lebih kuat. Cecil terbangun tepat ketika kami akan membedahnya, dan itu sangat merepotkan—asal kalian tahu.
Apa sekarang aku harus berurusan lagi dengan organ-organ menjijikkan itu? Kuharap tidak. Aku tidak pernah membanyangkan bagaimana rasanya menyetuh organ manusia secara langsung. Tidak pernah. Dan tidak akan. Aku sampai heran mengapa Bu Nadira bisa tahan menyentuh organ dalam itu tanpa menampilkan raut jijik sedikitpun—bahkan ia nampak bersemangat, pasti karena uang!
“Sebaiknya kalian pulang,” Si dokter sinting berkata pada Fino. Kata-katanya itu bagaikan angin segar bagiku. “Nadira, kamu bisa mengurus ini sendiri, kan?”
“Ya, ini sudah menjadi tugas saya, Dokter,” jawab Bu Nadira.
Aku bersyukur mereka mengerti keadaanku.
Fino mendengus, agak keberatan. Aku tahu ia membenciku. Tapi kurasa, tingkat kebenciannya padaku semakin bertambah dari waktu ke waktu. Yah, bayangkan saja, ia sudah seperti babby sitter-ku. Ia memmbangunkanku tiap pagi, membuatkanku sarapan dan bekal makan siang, dan ... mengantarku pulang ketika malam. Itu berat. Aku mengerti perasaannya. Padahal aku juga ingin hidup mandiri. Seandainya si dokter sinting lebih mengerti perasaan anaknya daripada berpura-pura menjadi ayah yang baik untukku, mungkin kebencian Fino padaku akan sedikit berkurang. Aku selalu berharap begitu.
“Ayo!” Fino menarik tanganku begitu saja ketika aku hendak membuka masker.
“Hey!” Aku memprotes, berusaha berontak. Namun genggaman tangannya begitu kuat hingga aku kesulitan melepasnya.
Kami sudah berada di luar ruang bedah ketika Fino melepaskan tanganku. Pintu ruang bedah ditutup dengan keras. Sekarang hanya ada kami di bawah tangga menuju lantai pertama, diselimuti kegelapan. Aku membuka maskerku dan membuangnya ke sembarang tempat. Aku kesal, entah kenapa.
“Kamu gila, ya?” semburku.
Fino menutup mulutku dengan tangannya. Sarung tangan bedahnya telah dilepas sehingga kulitnya bersentuhan langsung dengan bibirku. Sial!
Ia menyeretku ke sisi lain tangga. Kami masih diselimuti kegelapan. Ia mendudukkanku di salah satu sisi dan aku bisa mendengar suara deru napasnya. Ia baru saja melepas maskernya.
“Kamar mandinya ada di dalam, bodoh!” celaku.
“Aku tahu,” balasnya singkat. “Pelankan suaramu.”
“Lalu kenapa kamu menarikku keluar, huh? Kamu tidak berpikir untuk berjalan-jalan di luar sembari mengenakan pakaian bersimbah darah ini, kan?”
“Tadinya, aku memang ingin melakukan itu.”
“Kamu memang sudah gila!”
“Kamu juga. Aku hanya ingin kegilaan ini cepat berakhir. Aku hanya ingin kita cepat tertangkap—“
“Dan dieksekusi?”
“Hukum di negara ini melindungi kita. Kamu masih berumur 16 tahun dan aku 17 tahun. Kita masih dihitung remaja sehingga bebas dari jeratan hukum.”
“Tapi kita akan terpenjara.”
“Itu lebih baik. Setidaknya, pihak kepolisian akan mengeksekusi ayahku dan Bu Nadira. Sementara kita bebas. Kita bebas di dalam penjara. Setidaknya tempat itu lebih baik daripada neraka ini.”
“Lebih baik, huh?”
“Ya, Lidya! Tidakkah kamu berpikir bahwa lebih baik bahwa kita tidak usah menyembunyikan kejahatan yang telah kita lakukan dan dihukum dengan semestinya, daripada hidup enak tapi dengan cara yang tidak masuk akal seperti ini?”
“Aku tidak menyangka kamu masih secengeng itu, Fino. Jadi, kamu menyeretku ke sini hanya untuk mengutarakan pemikiran konyol itu?”
“Ya. Terserah kamu mau menganggapku apa. Yang penting, aku tetap kakakmu.”
“Kakak angkat,” koreksiku. Aku berdiri, hendak kembali ke ruang bedah dan mandi di dalam kamar mandi yang sedikit bau itu. Namun Fino menahan tanganku dan menyuruhku untuk kembali duduk di sisinya.
Mau tak mau, aku menurut. Fino masih menggenggam tanganku seolah-olah ia tidak mau kehilanganku. Aneh. Padahal aku yakin ia telah membenciku.
“Lidya,” ucapnya, masih dengan suara lirih. “Aku membencimu.”
Aku tersenyum, nyaris ingin tertawa. “Aku tahu.”
“Dan aku tidak pernah menganggapmu adik.”
“Aku juga tidak pernah menganggapmu sebagai kakak.”
“Tapi untuk sekarang ini, bisakah kita saling bekerja sama?”
“Bukankah kita bekerja sama sepanjang waktu, sebagai sesama korban?”
“Ya,” ucapnya singkat. Suaranya mengalun dengan lembut, terasa begitu dekat dengan telingaku. Aku bisa merasakan deru napasnya di leherku. “Kita hanyalah korban.”
Tubuh Fino yang dingin dan gemetar menempel pada tubuhku. Kedua tangannya melingkari punggungku. Kepalanya bersandar di bahuku. Aku hampir tidak percaya. Fino memelukku? Ia menangis. Aku bisa merasakan air matanya mengalir turun mebasahi pundakku. Aku bisa mendengar suara isakannya. Tapi suara itu begitu pelan. Mungkin Fino masih menahan diri.
Perasaanku bercampur aduk saat ini. Aku merasa bingung, sedih, marah, dan senang secara bersamaan. Tanganku bergerak melingkari punggungnya. Sesekali, aku menepuk-nepuk pelan punggung lebar itu, berusaha menenangkan Fino. Aku tidak mengerti. Badanku seperti bergerak sendiri. Fino seperti bayi kecil yang merengek dan aku adalah ibu yang melindunginya. Fino terasa seperti kaca yang rapuh dan aku adalah orang menjaganya dari segala hantaman. Aku merasa menang dan kalah secara bersamaan. Aku tahu Fino lelah. Aku juga. Tapi Fino lebih banyak merasakan lelah daripada aku.
“Lidya,” Fino berkata di sela-sela isak tangisnya. “Aku ingin tidur selama-lamanya, dan tidak pernah terbangun lagi.”
Aku ingin tertawa, tetapi urung. Aku memeluk Fino lebih erat, membiarkannya berlama-lama bersama isak tangisnya. Aku juga memikirkan hal yang sama seperti yang ia katakan.
“Ya, aku juga ingin tidur selama-lamanya, dan tidak pernah terbangun lagi,” ucapku. Suaraku begitu lirih. Amat lirih hingga aku sendiri hampir tidak bisa mendengarnya. Kata-kata itu melebur bersama udara, lalu hilang.Ya, hilang begitu saja.
***
Aku melirik arlojiku. Pukul 17.00. Semburat merah menghiasi langit. Sebentar lagi, senja akan berakhir. Tiba-tiba, rasa rindu menelusup ke dalam jiwaku. Dulu, di bukit belakang rumah, aku selalu melihat pemandangan yang sama bersama dengan ayah dan ibuku. Ah, ayah dan ibu? Tanpa sadar, air mataku mengalir begitu teringat kembali akan kenangan indah itu.
Dua tahun yang lalu, di bukit belakang rumah, aku bersama ayah dan ibuku bersama-sama menikmati senja sebagai perayaan ulang tahunku yang ke-14. Ibu membuatkan kami teh dan kue. Ayah dengan usil mengoleskan krim pada pipiku dan aku membalasnya. Ibu memarahi kami dan sempat terjadi pertengkaran kecil di antara kami. Namun akhirnya kami kembali akur dan tertawa bersama hingga matahari tergelincir sepenuhnya.
Aku tidak pernah menyangka bahwa pada hari yang indah itu, aku kehilangan kedua orang tuaku.
Saat itu, jam 11 malam, aku mendengar suara tembakan dari luar kamarku. Karena terkejut, aku terbangun. Kondisi rumahku amat gelap sehingga aku tidak bisa melihat apa-apa. Ketika aku menekan saklar lampu, lampu tidak menyala. Aku memanggil kedua orang tuaku. Namun, mereka tidak menjawab. Akhirnya, aku mengambil senter dari kamarku. Lalu, aku berjalan ke ruang tamu dengan diterangi cahaya senter.
Begitu sampai di ruang tamu, kakiku mendadak lemas. Bau anyir memenuhi ruangan. Darah membasahi lantai dan dinding. Perabotan rumah rusak dan kaca jendela rumah kami pecah. Orang tuaku tewas. Tubuh keduanya tergeletak di lantai bersimbah darah. Kepala dan dada mereka berlubang karena tembakan peluru. Sekeras apa pun usahaku untuk melupakan wajah mereka, peristiwa itu selalu terngiang di kepalaku hingga saat ini.
Setelah aku menemukan jasad kedua orang tuaku, tak lama kemudian, polisi datang dengan dokter gila bersama mereka. Mereka bilang, seseorang telah menelepon mereka dan berkata bahwa rumah kami dirampok. Polisi itu mengira bahwa akulah yang telah menelepon mereka. Namun aku tidak melakukannya. Si dokter gila mengadopsiku sehari setelah kejadian nahas itu. Namun, ia melakukannya dengan suatu tujuan. Ia ingin menjadikanku anak buahnya dan menjerumuskanku ke dalam dunia yang lebih gila. Dari situlah segala kisah menyedihkan ini bermula.
“Hei!” panggil sebuah suara.
Aku menoleh untuk mendapati Fino yang kini sudah berdiri di belakangku. Ia membungkuk, lalu menghapus air mataku. Aku tersentak. Segera kutepis tangannya.
“Ayo,” ucapnya dingin. Sikapku tadi rupanya dia abaikan. “Kta harus membedah korban baru malam ini.”
“Siapa korbannya malam ini? Salah satu teman sekelasmu?” tanyaku.
“Ya,” jawab Fino singkat.
Aku mengikuti Fino berjalan melewati ‘gang neraka’ seperti biasa hingga kami mecapai rumah mungil tempat kerja kami. Kami berjalan ke lantai bawah dalam diam. Ketika Fino membuka pintu laboratorium, dokter gila dan Bu Nadira menyambut kami seperti biasa. Seorang gadis tergolek lemas di ranjang bedah. Tubuhnnya penuh sayatan. Mungkin ia sudah sekarat.
Kami segera memakai masker dan sarung tangan. Tak lupa kami mengambil pisau bedah. Ya, pekerjaan kami kali ini adalah membedah tubuh gadis itu. Mungkin dokter gila membutuhkan jasaku untuk membunuh gadis itu dalam sekali tusuk. Ia tidak akan bisa melakukannya tanpa aku.
“Butuh bantuan?” tawarku pada dokter gila ketika kami sampai di ranjang bedah.
“Tentu. Gadis ini sedang tidak sadar sekarang. Lebih baik kau membunuhnya secepat mungkin,” jawab dokter gila.
Aku mengambil posisi di dekat dada kiri si korban dan mengangkat pisauku untuk menusuk lehernya. Namun tiba-tiba Fino meraih tanganku, lalu mendorongku menjauhi ranjang bedah hingga aku terjatuh. Detik berikutnya, aku melihatnya menerjang tubuh di dokter gila. Fino menyanyat leher dokter gila dengan pisau bedah yang ia bawa. Darah mengucur deras dari leher si dokter gila yang sudah tidak bernyawa. Aku terbelalak. Fino berbalik dan memandangku. Pakaiannya dibasahi oleh darah.
“Bocah sialan! Apa kau tahu akibat dari perbuatanmu, hah?” raung Bu Nadira.
Ia bergerak menerjang Fino dan menyayat bahu pemuda itu. Fino mengerang kesakitan. Tak puas, ia pun mencekik pemuda itu sambil mengucapkan sumpah serapah.
“Lidya, dialah yang telah membunuh kedua orang tuamu!” teriak Fino.
Aku terbelalak. Tak kusangka bahwa pembunuh orang tuaku yang sebenarnya adalah Bu Nadira. Dendam yang sudah lama kupendam bangkit ke permukaan. Dadaku sesak dipenuhi amarah. Aku bangkit berdiri. Kujambak rambut Bu Nadira hingga beberapa helai rambut tercabut dari kepalanya. Kutancapkan pisau bedah pada bahunya hingga ia meraung kesakitan.
Ia berbalik dan tangannya bergerak untuk mencekikku. Sebelum ia sempat melakukannya, Fino menendang tulang keringnya hinga ia terjatuh. Kemudian Fino menancapkan pisau bedah pada tengkuknya. Ia berteriak kencang. Aku membalik tubuhnya dan menusuk lehernya. Bu Nadira sudah tak bernyawa.
Aku dan Fino saling pandang. Selang beberapa detik kemudian, kami tertawa hingga suara tawa kami menggema di seluruh ruangan.
“Kerja bagus, kakak tiriku!” pujiku sembari mengarahkan kepalan tangan padanya.
“Kerja bagus juga, adik tiriku!” balasnya.
“Apa yang akan kita lakukan setelah ini?” tanyaku.
“Kabur.” jawabnya. “Mari kita pergi ke tempat yang jauh.”
Aku mengangguk. Kami bergegas menganti pakaian kami dan hanya membawa barang-barang yang perlu dibawa. Sebelum kami keluar, Fino tampak menelepon seseorang. Kami pun berjalan melewati ‘gang neraka’ seolah tidak terjadi apa-apa. Fino menghentikan sebuah bus dan kami menaikinya. Sirine polisi terdengar ketika bus yang kami tumpangi kembali melaju.
“Kamu menghubungi polisi?” tanyaku, berusaha sebisa mungkin memelankan suaraku di tengah-tengah rasa terkejutku.
“Iya,” jawab Fino tak peduli. Ia memasangkan earphone pada telinganya.
Aku menarik tangannya, membuatnya earphone yang ia pasang terlepas dari telinganya. “Apa yang kamu pikirkan?”
“Polisi perlu tahhu apa yang terjadi. Gadis yang menjadi korban juga akan terselamatkan.”
“Tapi kita juga akan tertangkap, bodoh!”
“Tidak akan,” ucap Fino sembari tersenyum. “Aku sudah merencanakan semua ini jauh sebelum kamu tahu.”
Aku memalingkan wajah darinya, menatap mobil-mobil yang melaju di jalanan. “Terserah.”
Kami sama-sama terdiam. Fino larut dalam alunan musik yang ia dengarkan melalui earphone, sementara aku kini sibuk memerhatikan rembulan yang berpendar sendirian di langit malam. Air mataku menitik. Pada akhirnya, janji yang diucapkan oleh dokter gila tidak akan pernah terwujud. Pada dasarnya janji itu memang hanya tipuan belaka. Dokter gila berjanji akan menghidupkan kedua orang tuaku asal aku mau membantunya. Karena itulah, aku dengan bodohnya mengikuti semua perintahnya hingga meninggalkan sisi manusiaku. Kini, semua sudah berakhir. Aku termangu menanti nasib kami berikutnya, menunggu bis yang kami tumpangi membawa kami entah ke mana.
TAMAT


 Mustikaningtyas
Mustikaningtyas





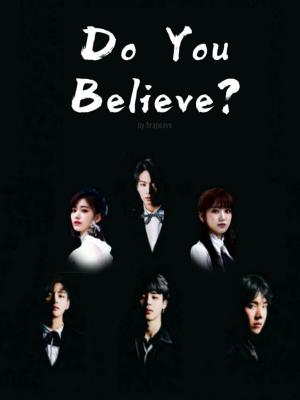




@Lovender yak sesuai judulnya.