Dio memasukkan tangan ke saku celana, berjalan santai menembus keramaian. Hari pertama tahun ajaran baru ini sekolah riuh tak wajar. Bukan cuma murid-murid yang memadati halaman depan SMA Waditranagara (atau lebih umum disingkat Wadit), tapi juga beberapa kelompok 2-orang yang komponennya identik: satunya wanita cantik dengan mikrofon di tangan, satunya lagi pria dengan kamera di pundak.
“Dek, bisa minta waktunya sebentar?” satu suara tiba-tiba menyambut Dio, sebuah mikrofon berwarna biru berlogo salah satu stasiun TV lokal teracung ke arahnya.
“Nggak,” jawab Dio pendek, kemudian lanjut melangkah, masih dengan air muka datar. Si Mbak cantik spontan tertegun.
Namun, Dio belum sepenuhnya bisa lega. Setelah mbak-mbak barusan, berdatangan wartawan lain mengacungkan mikrofon ke arahnya. Dio mengangkat tangan, terus-terusan memberi jawaban negatif, sambil dalam hati bertanya-tanya mengapa dia merasa seperti jadi pejabat kena skandal. Memang susah sih kalau punya penampilan keren (—menurut sebagian besar cewek. Kalau cowok-cowok sih cenderung menyebutnya songong).
Ngomong-ngomong soal wartawan, sejak dua hari lalu mereka mengerubuti parkiran Wadit seperti lalat menemukan kotoran. Pasalnya, waktu itu terjadi tawuran besar-besaran di dekat Wadit yang memakan korban cukup banyak korban: mobil-mobil rusak berat, rumah-rumah kehilangan kaca dan pagar, sebuah kafe dijarah. Puluhan orang luka berat. Lima tewas. Dan karena kejadiannya di dekat salah satu sekolah populer, jadilah bahan sorotan dan spekulasi.
Bahwa tawuran ini dilakoni oleh siswa-siswa Wadit sendiri.
Belum ada klarifikasi dari manapun soal itu sehingga rumor pun simpang siur.
Salah satu imbasnya adalah para orang tua murid yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Dialog dengan pihak yayasan dilakukan. Masalahnya, sulit melacak apakah ada anak Wadit yang bergabung dalam bentrokan itu. Kalau ditanya satu-satu kan mana mungkin ada yang ngaku. Bukti pun tidak ada. Lagipula, pihak yayasan bersikeras memercayai murid-murid mereka; karena benar-benar bisa menjatuhkan reputasi kalau terbukti ada anak Wadit yang ikutan, atau malah menginisiasi tawuran. Tidak ada yang suka diingatkan akan kejadian sepuluh tahun lalu. No, thank you very much.
Intinya, karena belum ada kesepakatan dengan pihak yayasan, sebagian orang tua memboikot kelas dengan tidak mengizinkan anak-anak mereka datang. Malah ada yang mengancam akan memindahkan anak mereka ke sekolah lain.
Begitu media mengetahui soal ini, makin rusuh deh jadinya.
Dio mengikuti kabar teraktual secara pasif. Dia memutuskan untuk tidak ikut ambil pusing, apalagi kalau anak itu tidak terlibat. Maka, hari Senin yang cerah ini dia pun pergi sekolah dengan semangat yang biasa—postur santai dengan muka mengantuk.
Dio akhirnya terbebas dari todongan mikrofon ketika sebuah mobil hitam mentereng memasuki pelataran parkir. Para wartawan terpaku sesaat, kemudian segera bergerombol di sekitar mobil yang sudut-sudutnya memantulkan cahaya matahari pagi itu. Dio ikut berhenti, mengawasi.
Tiba-tiba seseorang dari tengah kerumunan itu berteriak, kemudian terjadi saling dorong dan saling sikut. Dua bodyguard berbaju hitam-hitam membelah kerumunan diikuti seorang gadis cantik berseragam Wadit. Dua lagi bodyguard mengikuti di belakang mereka, membentuk perisai sambil menghalau acungan mikrofon.
Nyai Raden Nadia Crowleister Brahmadibrata—Sang Puteri. Tentu saja. Di antara semua anak Wadit, pastinya cuma dia yang paling merasa aman datang ke sekolah pada masa tegang begini.
Dio melanjutkan berjalan. Dia berhenti lagi di depan papan pengumuman untuk melihat pembagian kelas yang baru sambil setengah berharap tidak satu kelas lagi dengan satu pun teman sekelasnya tahun lalu. Walaupun sudah bersikap tidak bersahabat, selalu ada saja orang yang tak pandai membaca suasana dan secara rutin menggerecokinya. Sepanjang tahun. Entah itu mengajaknya aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, atau mengajaknya makan bareng pas istirahat, atau mendatangi rumahnya saat dia bolos sekolah.
Meskipun demikian, apapun yang diharapkan Dio, yang jelas dia tak mengira akan menemukan dua nama itu di daftar siswa kelasnya.
Ken Ratu Puspawardhana. Kemudian, tepat di bawahnya, Nadia.
Seorang mantan ketua preman sekolah dan seorang tuan puteri. Jelas ini kombinasi teman sekelas yang tidak akan ditemui dimana pun kapan pun selain di sini, sekarang.
Selain dua nama itu, Dio tak mengenali nama-nama lainnya. Jarinya melayang ke dagu, menggaruk-garuk. Dio tidak ingin mengakuinya, tapi sedikit bagian dari dirinya merasa antusias menghadapi tahun mendatang.
Mungkin, tahun ini akan menarik.
~ ~ ~
Perkiraan Dio salah. Tak perlu menunggu setahun untuk menyaksikan kejadian menarik. Dia sedang duduk di kursi pilihannya, kursi paling belakang di sebelah jendela, ketika hal itu terjadi.
Saat sedang tenang-tenang menuliskan namanya di buku catatan, seseorang menendang kaki mejanya sehingga pulpen Dio malah membuat goresan panjang, setengah merobek lembar pertama. Dia sudah mau membentak siapapun yang sembrono itu, saat dilihatnya seorang gadis tengkurap di lantai tepat di sebelahnya.
Bukan, bukan sembarang gadis.
Sang Puteri.
Dio, dan anak-anak lain yang sedang nongkrong di dalam kelas, mematung sesaat. Kemudian, saat Nadia akhirnya bergerak dan mengangkat tubuhnya, bisik-bisik memenuhi ruangan. Tak ada yang berani terang-terangan menertawakan Sang Puteri, tapi dari bisik-bisiknya saja sudah jelas mereka menganggap kejadian barusan lucu.
Dio, yang bete, jadi tidak tega saat dilihatnya Nadia mengusap pipinya dengan punggung tangan, kemudian tercenung menatap sesuatu berwarna merah mewarnai kulit putihnya. Tangan yang sama dihiasi sebuah cincin di jari manisnya.
Pasti pipinya tergores saat tangannya mencoba menyelamatkan wajahnya dari mencium tagel. Naas banget sih nih Puteri satu, pikir Dio.
Terdorong rasa kasihan, Dio meletakkan pulpennya dan berpindah posisi: berjongkok di depan Nadia yang masih terduduk di lantai. Di pipinya nampak goresan sepanjang sekitar dua senti, darah merembes keluar dalam bentuk bulatan kecil. Ketika Dio membantunya bangun, cewek itu terbelalak menatapnya. Dio tidak tahu apakah itu ekspresi terkejut, takut, atau marah.
Peduli deh, selama dia tidak ribut-ribut.
“UKS,” kata Dio singkat, mendorong Nadia menuju pintu. Tanpa kata, Nadia menurut.
Saat sampai di pintu, wajah familiar lain muncul di hadapan mereka. Mereka mematung sesaat, saling memandang.
“Dio, kamu apain dia?!” anak itu tiba-tiba meradang, melihat cewek mungil di depannya berdarah-darah.
Perlu dua detik bagi Dio untuk mengenali anak itu.
Cewek di depannya sudah pasti Ken, tak salah lagi. Namun, tak seperti Ken yang diingatnya, cewek di depannya ini punya rambut panjang yang dibiarkan tergerai, mengenakan kacamata, dan seragam yang dikenakannya… begitu rapi dan licin sampai terlihat sangat cupu. Roknya bahkan panjang sampai setengah betis.
“Ken?” Dio mengangkat alis, tidak percaya mata kepalanya sendiri.
Anak itu melotot.
Memang Ken. Kulitnya yang agak gelap karena sering dijemur, perawakannya yang ramping berotot, dan yang pasti sorot matanya yang setajam elang, walaupun sekarang agak dilunakkan dengan kacamatanya.
Ngomong-ngomong… sejak kapan Ken pakai kacamata?
Berlawanan dengan penampilannya yang ala kutu buku, Ken tiba-tiba saja mencengkeram kerah kemeja Dio, lalu mendekatkan wajah, bibir menyumbing.
“Kamu baru ngapain, haaaah?”
“Woi, bukan gue—ntar, ‘kamu’? Sejak kapan lo nggak nge-lo-lo-in orang?”
“Saya jatuh sendiri kok,” kata Nadia lemah. “Mas ini malah nolongin saya.”
Mendengar kesaksian Nadia, Ken buru-buru melepaskan Dio, lalu celingukan seperti maling takut ketauan. Koridor sedang sepi karena anak-anak pada menunggu bel jam pertama di dalam kelas—lagipula, memang tidak banyak yang datang hari ini. Yang sedang berada di koridor tidak melihat ke arah mereka.
“Nih, sana bawa ke UKS,” katanya pada Ken, ‘menyerahkan’ Nadia. Dia sendiri kembali masuk kelas. Sekilas didengarnya Ken mengajak Nadia berkenalan, berbincang sebentar, lalu keduanya melangkah pergi.
Saat mereka kembali, darah di wajah dan tangan Nadia sudah dibersihkan, dan dia bukan cuma dipasangi plester di pipi, tapi juga pergelangan tangannya diperban. Terlambat lima menit, guru wali kelas mereka—rupanya Pak Marzuki, guru olahraga yang lebih killer daripada guru matematika dan dipanggil Bos oleh anak-anak karena style batik Cirebonnya—hampir saja mau memarah-marahi Ken, yang masuk duluan. Begitu dilihatnya Nadia mengikuti Ken, beliau langsung tenang.
Pak Marzuki digosipkan lemah sama cewek cantik, tapi menurut Dio, guru berpenampilan seram itu lebih takut pada status Nadia sebagai seorang Brahmadibrata daripada luluh pada paras ayunya.
Ken berjalan ke arah Dio, sempat-sempatnya mencibir sebelum dia berbalik dan duduk di kursi di depan Dio. Dosa apa gue, pikir Dio, memerhatikan Ken sejenak. Terakhir dia bicara dengan Ken adalah sebelum ujian kelulusan SMP, lebih dari setahun yang lalu. Waktu itu rambut Ken model shaggy pendek. Seragam sekolahnya kumal karena dia jorok dan kebanyakan berantem. Roknya juga pendek, dengan celana trening di baliknya yang memudahkannya bergerak bebas. Tomboi banget pokoknya.
Kok sekarang jadi kelihatan seperti murid teladan begitu (yah, kalau kelakuan sih sepertinya masih agak barbar)?
Nadia, yang masih kelihatan lost, baru sadar kalau dia masih mengekori Ken begitu Ken duduk. Dengan geragapan, dia segera duduk di kursi di depan Ken.
Bos menunggu Ken dan Nadia duduk sebelum melanjutkan.
“Nah, kembali lagi ke topik,” katanya, meraih ke dalam tas yang dibawanya dan mengeluarkan setumpuk buku tulis. “Masing-masing kelompok akan menulis jurnal di dalam buku ini dan mengumpulkannya setiap hari Senin pagi. Buku-buku ini akan saya kembalikan—“
“Kelompok apaan?” Ken tiba-tiba berbalik, berbisik kepada Dio.
Dio baru akan membuka mulut untuk menjawab ketika matanya menangkap sesuatu berwarna putih melayang ke arah mereka.
Pletak!!
“AWW!” Ken spontan memekik. Sebuah spidol telah disambit ke keningnya. Proyektil yang bersangkutan jatuh berkelotakan di lantai.
“Kamu punya pertanyaan, Ken Ratu?” tanya Bos.
Ken, meringis dan mengusap dahinya, terlihat terperanjat, menoleh antara Bos dan Dio bergantian.
“Kenapa, hmmm?” tanya Bos lagi, terdengar mengancam.
“Ng-nggak, Pak… nggak ada…”
Bos memelototinya selama beberapa detik sebelum melanjutkan penjelasan. Beberapa anak di kelas mengeluarkan bunyi seperti menahan tawa, tetapi tidak berani keras-keras karena Bos nampak sangat menyeramkan.
“Nah, jadi, bukunya akan saya kembalikan pada waktu istirahat makan siang. Kalian boleh menulis apa saja di dalam buku ini. Tapi harap diingat, saya akan baca semuanya, dan kalau kerja sama kelompok kalian tidak ada tanda-tanda meningkat, nilai akhir kalian akan kena penalti.”
Dio mendengar tarikan napas tajam di beberapa tempat di seluruh ruangan. Pasti anak-anak ingin berkomentar tentang betapa konyolnya aturan yang akan diberlakukan itu, tetapi tidak berani bersuara.
“Nah,” Bos memulai lagi. Dia membawa buku-buku tulis di tangan lalu berjalan ke kolom pertama dari pintu masuk. Dia menaruh sebuah buku di meja paling depan. “Kamu dan dua teman di belakangmu satu kelompok,” katanya.
Si anak yang menerima buku itu menoleh ke belakangnya. Dua bangku di belakangnya kosong. Bos memberikan buku yang kedua kepada anak yang duduk di baris keempat.
“Kamu dan dua teman di belakangmu satu kelompok.”
“Pak, tapi kursinya masih kosong,” si anak yang duduk di baris pertama memberanikan diri protes.
“Yasudah, nanti kalau sudah ada yang ngisi, kamu kasih tau mereka kalau kalian sekelompok,” jawab Bos enteng. Kemudian dia menghadap seluruh kelas, menatap anak-anak yang datang hari pertama ini satu persatu. “Sampai saya bilang boleh, kalian tidak boleh pindah tempat duduk!”
Kemudian, Bos lanjut memberikan buku-buku, dan meletakkan buku di atas meja kalau ketiga bangku yang dikelompokkannya belum dihuni.
Ken berbalik lagi kepada Dio, kedua matanya terbelalak lebar di balik kacamata berbingkai perseginya. Dio mengerti maksud pandangan itu.
Mereka bakal sekelompok kalau begini caranya.
Sebenarnya sih, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi melihat ekspresi Ken yang jelas-jelas bilang nggak mau sekelompok dengannya, batin Dio jadi tergelitik. Biasanya dia yang enggan berkelompok dengan orang lain. Orang lain lah yang selalu menawarkan satu kelompok dengannya.
Dengan gaya pongah yang dia yakin akan membuatnya menyesal di kemudian hari, Dio memberi Ken sebuah seringai puas.
Anak itu langsung terlihat putus asa.
Emang apa salahnya sekelompok sama gue? pikir Dio. Dio memang tidak termasuk murid unggulan, tapi dia juga nggak bontot. Malah, seingatnya, sejak SD ranking dia selalu lebih tinggi daripada Ken. Jadi harusnya anak itu bersyukur dong.
Pluk—
Bos memberikan buku terakhir kepada Nadia. “Kalian bertiga satu kelompok,” katanya, bola matanya bergulir ke arah Ken dan Dio. Bos kemudian kembali berdiri di mimbar.
“Nah, ada pertanyaan?”
Hening.
“Bagus. Saya menunggu isi jurnal kalian setiap Senin pagi. Nah, karena situasi sekolah masih runyam, jadwal pelajaran kalian belum selesai disusun. Jadi untuk hari ini, kalian belum ada kelas. Nah, kalian boleh langsung pulang.”
Berita yang biasanya disambut sorakan meriah, hanya ditanggapi dengan kesunyian.
Begitu Bos meninggalkan kelas, anak-anak langsung bergerombol dengan teman-teman mereka, membicarakan perihal kelompok-kelompok yang baru saja dibentuk secara semena-mena. Ada yang mengeluh, ada yang berharap teman sekelompok yang tidak datang hari ini ternyata orang yang bisa diandalkan, atau kecengan mereka, dan sebagainya.
Ken, yang sudah tidak tahan ingin bersuara dari tadi, langsung berbalik menghadap Dio.
“Masa kita satu kelompok?!” serunya.
“Emangnya kenapa?”
“Emang ini kelompok apaan sih?”
“Jadi lo protes tanpa tau itu?”
“Ya pokonya kalo bisa milih sih aku ga sudi sekelompok sama kamu!”
Dio merasa seperti baru disambit simbal. Doengggggggg—
“Itu sih masalah lo. Lagian, ngapain duduk di depan gue? Kursi lain masih banyak gitu!” tembak Dio.
Ken membuka mulut.
Terdiam sedetik. Menutupnya lagi. Mati kutu.
“Anu…” sebuah suara pelan menyela. Nadia, kelihatan gugup dan takut-takut, mengulurkan buku yang tadi diberikan Bos kepada Ken. “Ngg… ini… bukunya…”
“O-oh… iya…” jawab Ken. Selepas serah terima buku, keduanya terdiam, bingung mau bicara apa. Dio menunggu beberapa saat, namun tak satu pun di antara kedua cewek itu yang buka suara lagi.
Dio menghembuskan napas keras-keras.
“Intinya,” kata Dio, “Bos punya program meningkatkan prestasi kelas kita. Caranya, kita semua dibikin kelompok-kelompok dan wajib curhat di buku itu.”
“Ih,” respon Ken, memandang buku di tangannya dengan jijik. “Trus Bos baca curhatan kita?”
“Ya lo nggak usah curhat aneh-aneh juga kalee,” Dio memutar bola mata. “Lo nggak usah bilang kalo ketek lo buluan atau lubang idung lo gede sebelah.”
“Kasih contoh bagusan dikit napa!” Ken menukas, tapi sambil bercermin ke layar handphone-nya yang tidak menyala.
“Ya lo kan agak-agak bolot, jadi mesti ekstrem.”
“Kamu tuh udah lewat berapa tahun masih juga nyebelin ya. Ngomong-ngomong, sejak kapan kamu sekolah di sini? Kok aku nggak inget pernah liat kamu.” Ken mengernyit sambil mengusap dagu.
“Gue juga nggak inget liat lo, kampret,” sahut Dio. “Lo ngapain sih ngikut-ngikut gue mulu?”
“Enak aja, siapa yang ngikut-ngikut? Kamu tuh!”
“Ngapain gue ngikut-ngikut elo? Gak elit tau nggak!”
“Trus kok kamu bisa nggak pernah liat aku? Emang kamu nggak ikut milih?”
Dio mengerutkan kening.
“Milih apaan?”
“Ketua OSIS.”
Dio makin terperangah. “Elo? Ketua OSIS?!!!”
“Iya, aku ikut nyalonin diri pas akhir tahun kemaren. Foto aku kan dipajang gitu! Masa kamu nggak pernah liat?!!”
Kalau dipikir-pikir, rasanya memang Dio pernah melihat foto orang dengan ciri-ciri yang sama dengan Ken saat ini. Tapi karena image Ken yang diingat Dio bukanlah tampang kalem dengan senyum lebar, rambut panjang, dan kacamata, Dio tidak tergerak untuk benar-benar melihat poster kampanye itu. Dio kan tidak tertarik soal hal-hal berbau hubungan antarmanusia seperti itu.
“Berarti kamu beneran nggak milih ya? Nggak pernah dateng debat terbuka? Mana rasa tanggung jawab kamu sebagai pemegang hak pilih? Kamu tau nggak seberapa pentingnya satu suara? Itu tuh bisa jadi suara yang menentukan aku menang atau enggak!!!”
“Dengan kata lain lo kalah pemilihan?” simpul Dio.
Ken menatap Dio dengan pandangan menyalahkan. “Iya, dan itu pasti gara-gara kamu!”
“Emangnya persenan pemilih kalian berapa?” selidik Dio, entah mengapa bisa menebak jawabannya.
“...Sembilan lima lawan lima,” jawab Ken dengan suara kecil.
“Itu sih elo emang nggak populer!”
“Tapi sebenernya emang yang golput lebih dari setengah total suara sih.”
“Demokrasi yang nggak jalan ya,” kata Dio. “Anak-anak Wadit tuh emang bukan tipe demen organisasi sih. Bau rumus, kalo enggak bau badan.”
“Nggak sopan!” tukas Ken.
“Ng… anu…” Nadia mengangkat tangan.
Ken langsung beralih persona dari kandidat yang kalah pemilihan jadi teman sekelas yang baik hati. “Eh, iya, kenapa?”
Nadia kelihatan ragu-ragu mau ngomong. Wajahnya terus menunduk. Apakah dia malu karena kejadian konyol tadi pagi? Kalau Dio sih pasti tengsin keliatan jatuh tengkurep kayak mau nangkap kodok begitu.
“Ngg… nggak apa-apa,” kata Nadia buru-buru. “Maaf, mengganggu.”
Ken terbelalak. “Eh? Enggak! Enggak kok, nggak ngeganggu?”
Kenapa ngomongnya pake tanda tanya, pikir Dio sambil menyandarkan dagu ke tangan.
“Iya…” Nadia mengangguk.
Lalu terdiam.
Dio mengakui dirinya antisosial, tapi melihat dua cewek di depannya berhadapan dengan kikuk, dia jadi merasa sangat ekstrovert. Dia merasa begitu kasihan sampai-sampai, sebelum sempat mempertimbangkan apa yang sedang dilakukannya, dia sudah berkata,
“Jadi, mau ngobrolin soal kelompok kita?”
~ ~ ~
“Ehem,” kata Ken, setelah menyeruput iced lemon tea-nya sampai habis dalam sekali sedot. “Kita mulai dari… ngg… perkenalan kali yah?”
“Hm,” Dio mengeluarkan bunyi sambil mengunyah batagor.
Nadia mengangguk kecil. Dia masih saja menunduk, tidak mau menatap baik Dio maupun Ken. Mau tak mau Dio jadi kepikiran. Nggak cocok aja kalau orang sekaliber Nadia ternyata gugupan. Biasanya orang itu pemalu atau gugupan karena nggak pede. Lantas Tuan Puteri nggak pede apa? Dia cantik. Semua orang tahu seperti apa tampangnya di balik rambut panjang berwarna emas merona yang selalu merumbai ke depan wajahnya itu.
Dia juga pintar. Ranking sepuluh besar seangkatan selalu diumumkan ke seantero sekolah pada setiap akhir semester, dan nama Nadia selalu disebut.
Dan soal status sosial, itu sih udah nggak usah ditanya. Cuma orang yang tinggal di dasar laut yang tidak tahu soal Brahmadibrata.
Mungkin dia masih malu soal jatuh tadi ya? Dia jatuhnya cakep kok, roknya tidak sampai tersingkap dan kaki-tangannya tidak mengacung ke segala arah seperti kodok beneran. Dio bakal jadi orang pertama yang terbahak-bahak kalau sampai kejadiannya begitu.
“Aku Ken Ratu Puspawardhana,” kata Ken, memulai. Dia mencoba menatap Nadia melewati poni tebalnya, tetapi akhirnya malah balik menatap Dio. “Sebelumnya aku kelas 1B. Sekarang aku jadi wakil ketua OSIS—“
Omongan Ken terputus ketika Dio menyela.
“Bukannya lo kalah pemilihan?” tanya Dio.
Ken memberi Dio pandangan merendahkan. “Yang nunjuk wakil ya ketua yang terpilih.”
“Oh gue tau. Si ketuanya kasian ya sama lo, jadi dia milih lo.”
Bletak! Tinju Ken langsung menghantam ubun-ubun Dio.
“Sakit, kamprettt!!!”
“Aku paling suka pelajaran Biologi trus paling nggak suka TIK.”
“Bukannya lo paling suka olahrag—EIT!!” Dio buru-buru berkelit ketika tangan Ken melayang lagi ke arahnya.
“Diem, cumi! Hobi aku baca”—Ken mendelik, seolah-olah menantang Dio untuk berkomentar lagi—“sama olahraga. Apa lagi ya? Rumahku di daerah Tirtakencana. Ada yang mau ditanyain?”
Dio ingin meledek, tapi urung karena masih sayang kepala.
“Giliran kamu,” kata Ken kepada Dio.
Dio mendesah. “Harus ya?”
“Aku sih nggak peduli, tapi Nadia kan belum kenal kamu.”
Dio memutar bola mata. Maka dia pun membetulkan posisi duduknya sehingga menghadap Nadia. Anak itu pun menghadap Dio lurus-lurus, masih setengah menunduk. Namun, sekarang wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya putih berseri, persis deskripsi Puteri Salju. Plester di pipinya tidak mengurangi kecantikannya. Sepasang matanya bundar besar, berwarna biru terang, dinaungi oleh alis tebal dan bulu mata lentik. Rambutnya panjang tebal dan bergelombang. Hidungnya mungil dan bibirnya merah ranum.
Berhadapan dengannya langsung, Dio jadi bertanya-tanya, apakah yang ada di depannya itu manusia, atau boneka.
“Hei, malah bengong!” kata Ken, mengetok meja.
Dio mendelik, cemberut. “Gue Dio. Tahun lalu gue—“
“Nama lengkap dong,” sela Ken.
Dio mendecakkan lidah tak sabar. “Dionysus Düsseldorf. Dulunya kelas 1G. Gue nggak suka pelajaran apa-apa. Nggak ikut ekskul apa-apa. Hobi tidur. Cukup?” pertanyaan ditujukan kepada Ken, yang bersidekap dengan sebelah alisnya terangkat.
“Kamu kok kayak kakek-kakek udah pensiun aja, nggak ngapa-ngapain.”
“Sialan lo.”
“Kamu juga ngata-ngatain aku tadi!”
“Ya elo sih emang penuh dengan bahan buat dikata-katain.”
“Kayak yang kamu perfect aja!”
“Wah, lo tau apa artinya perfect?”
Bletakk!
“Wanjrottt!!” Dio memekik. Segelintir orang yang sedang nongkrong di kantin jadi menoleh ke meja mereka.
Sementara itu, mengusap-usap kepalanya, Dio melirik Nadia, yang masih diam saja.
Namun, kali ini ada binar yang lain di matanya. Seperti… terkesan? Dio mengerutkan kening. Jangan-jangan Sang Tuan Puteri punya tendensi sadis? Suka melihat orang disiksa?
“Ngg…” kata Ken kepada Nadia, tiba-tiba jadi canggung. “S-sekarang giliran kamu.”
Ekspresi terkesan sirna dari wajah Nadia, menyisakan takut.
“Um… nama saya… um… Nadia… Brahma… dibrata…” dia memulai dengan nada tidak yakin. Dio menelengkan kepala, menahan komentar. “Sebelumnya… um… kelas 1A. Um… saya suka… um… pelajaran bahasa. Um… kurang suka Matematika. Hobi saya… um… um…”
Nadia kelihatan berpikir keras. Dio tidak mengerti mengapa orang bisa bingung menyebutkan hobi mereka, tapi berhubung menyebut nama sendiri saja Nadia terdengar ragu, bagaimana menyebutkan yang lain.
“Saya… suka… violin,” kata Nadia akhirnya.
Ken mengangguk-angguk. Dio bertopang dagu.
Hening.
…
…
Dio gemas sendiri melihat personifikasi kekakuan di depan matanya. Dia menyerah jadi anggota pasif. Setidaknya saat ini. “Jadi, udah nih kenalannya?”
Ken mengerutkan kening. “Kayaknya kurang ya?”
“Lo mau tau apa lagi?”
Bukannya menjawab, Ken malah menggebrak meja. “Oke!” katanya keras.
Firasat Dio nggak enak.
“Apanya yang oke?”
“Ayo kita main!”
“Main apaan?”
“Hem… padahal hari ini mumpung nggak ada pelajaran ya… tapi tadi aku dapet SMS disuruh kumpul OSIS…”
“Rajin banget hari pertama masuk udah kumpul?” komentar Dio.
Ken menggebrak meja lagi. Sepertinya dia merasa kurang jadi diri sendiri kalau tidak menggunakan tangannya untuk memukul sesuatu. Dio tidak akan mengeluh selama yang jadi objek pemukulan bukan kepalanya. “Iyalah! Emang kamu lupa? Pengurus OSIS yang baru kan punya tugas manitiain pameran!”
Dio melirik langit-langit. Ken menggerutu tidak sabar.
“Pameran Karya Waditranagara! Itu kan acara besar-besaran yang setiap ekskul dan kelas bikin karya. Event terbesar Wadit, dan keberhasilannya mencerminkan kecakapan ketua OSIS yang baru terpilih. Acara yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat kita!”
“Lo yakin ini acara yang ditunggu-tunggu?”
“Emang taun lalu kamu nggak dateng? Dulu waktu Kak Artemis jadi ketua OSIS Wadit, kita kan dateng, Di!”
Barulah Dio terlihat seperti orang yang menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan.
“Oh, acara itu. Jadi itu acara tahunan?”
“Iyaaaaa! Parah, masa baru tau?! Tahun lalu kelas kamu nggak bikin apa-apa?”
“Tahun lalu gue mangkir.” Dio samar-samar ingat kelasnya heboh membuat patung tanah liat segede gaban untuk dipamerkan tahun lalu. Kirain itu tugas Seni Rupa. Pantes nilai Seni Rupa gue tetep jelek…
Ken menghembuskan napas berat, menggeleng-geleng. “Kamu itu ansosnya nggak ada batasnya ya?”
Dio mengangkat bahu, cuek.
“Weekend deh yuk? Mau nggak?” Ken kembali ke pembicaraan sebelumnya. “Jalan-jalan bareng. Kita bertiga. Gimana?”
Dio cepat-cepat menolak. “Ken, weekend itu hari libur!”
Ken mengangkat sebelah alis. “Terus?”
“Waktunya tidur! Lo paham kan? Libur, tidur. Berima. Pas!”
“Pft…” Nadia menahan tawa. Dio meliriknya, agak kaget karena Sang Puteri tiba-tiba memberi reaksi. Kedua matanya melengkung membentuk bulan sabit. Bibirnya tersembunyi di balik tangannya, namun dia jelas-jelas sedang tersenyum.
Ken dan Dio bertukar pandangan. Kalau tidak sedang menunduk seperti bebek takut disembelih, Nadia benar-benar terlihat memesona!
“Okee weekend ini ya!” kata Ken bersemangat.
“Argh. Pokoknya gue nggak ikut!” kata Dio keras kepala.
“Hei, kita ini harus kompak! Kamu inget nggak kata Bos? Kalau kita nggak kompak, nanti nilai akhir kita kena penalti!”
Dio mengusap dagu. “Iya juga ya. Nilai lo udah jongkok, bisa langsung rebahan kalo kena penalti.”
Dio harusnya tahu bahwa lebih baik tidak mengatakan hal itu.


 drei
drei






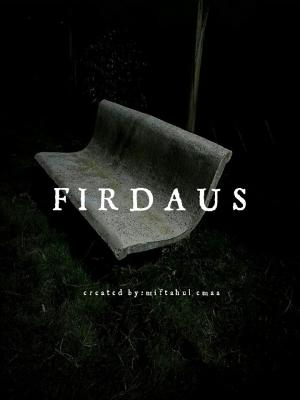



95 banding lima, auto sakit perut ketawa cekikikan. Tenyata kalau di perhatiin tokoh Ken, karakternya hampir mirip dengan, tokoh Tio di ceritaku.
Comment on chapter Satu