Hujan turun membabi buta hari ini. Datang tiba-tiba dari balik awan kelam yang tersedu. Begitupun Liam yang kini tak menyangka akan presensi Arun yang sejak tadi bersamanya di bawah naungan halte bus sebagai peneduh.
Bahkan Liam pun tak bisa menampik jika dia merasa gusar dalam posisinya. Mengarahkan atensi saja pada sepupu laki-lakinya itu ia tak bisa, apalagi harus bersuara hanya untuk menyapanya. Walaupun sekilas lirikan Liam sempat mendarat pada wajah Arun, laki-laki di sebelahnya itu nampak memasang wajah tak bersahabat. Dari samping wajahnya pun tak terlihat sedikitpun ada garis bibir yang hendak tersenyum, atau bahkan gerak-gerik untuk mulai menyapa Liam juga tak ada.
Liam dan Arun bukan tanpa alasan bersikap demikian, meskipun katakanlah mereka bersepupu, memiliki kakek dan nenek yang sama. Namun jika menilik pada situasi yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin untuk saling berbagi ucapan bukanlah pilihan yang baik.
Hening mendominasi dalam dua puluh menit kedepan. Hanya rintik hujan yang mau bersuara. Dari tadi tak ada seorang pun yang nampak berlalu lalang di pinggir jalan, atau bahkan menghentikan langkahnya untuk bergabung bersama mereka sedekar berteduh pun sama sekali tak ada. Dan hal ini yang makin membuat Liam tak nyaman.
Katakanlah Liam bisa saja pergi menghindari situasi yang pelan-pelan membunuhnya ini dengan menerobos hujan yang mungkin akan membuatnya demam setelah ini, tapi Liam bukanlah orang yang suka mengambil resiko. Bukankah menerobos hujan akan membuatnya terlihat semakin bodoh?
Semakin Liam menahan situasi canggung yang seolah membuatnya akan mati, pelan-pelan bisikan akan dirinya yang lain terdengar samar-samar masuk dalam pikirannya. Bisikan itu tak lebih adalah Bicaralah dengannya, dan selesaikan ini dengan cepat.
Tak butuh waktu lama bagi Liam untuk mengimplementasikan bisikan tersebut, karena sedetik bisikan itu merasuki kepalanya, ia langsung menoleh.
Liam terdiam sejenak saat pandangan matanyanya sukses mendarat pada bagian kiri wajah Arun, dan melihat beberapa raut Arun yang kemudian bergerak tak nyaman membuat Liam yakin, akan Arun yang menyadari pandangannya.
“Sekarang katakan, apa yang bisa dikatakan,” ucap Liam. Satu-satunya kalimat pembuka dalam percakapan ini.
Arun masih mengunci posisinya. Hanya memberikan sebuah helaan napas kasar sebagai balasannya.
Menyadari Arun yang tak memberikan respon yang baik, Liam kembali mengarahkan pandangannya ke depan. Menatap rintik hujan yang terus saja berjatuhan.
“Masih terus berkeras kepala ternyata.” Ada sebuah sindiran tawa kecil di akhir ucapan Liam.
“Setidaknya jangan bersikap seperti anak kecil. Kalau ada yang salah, apa susahnya menjelaskannya? Bukan menjadi seseorang yang mendadak berbeda, dan dengan alasan yang tidak jelas langsung membenciku.” Ucapan Liam barusan sukses membuat rahang Arun sedikit menggeram.
“Setidaknya biarkan gue tahu alasannya.” Liam kembali menoleh, menuntut sebuah penjelasan singkat dari Arun. Namun laki-laki itu tetap saja terdiam, hingga memaksa Liam untuk berucap “Arun!”
“Tidak ada.” Itu satu-satunya jawaban yang keluar dari bibir Arun. Singkat, dan intonasinya cenderung merendah.
“Gue tidak sebodoh itu,” timpal Liam.
“Bukan urusanmu.”
“Jelas-jelas ini juga urusanku.”
Arun hanya mendecih selepasnya. Tak dapat memberikan keterangan yang Liam butuhkan.
“Membakar buku catatanku di belakang sekolah, merobek blazzerku di dalam locker, menumpahkan oli di tempat dudukku. Cih, ternyata lo cukup kenak-kanakan untuk seseorang yang berusia tujuh belas tahun,” perjelas Liam. Kali ini tidak menatap pada Arun.
“Untuk seseorang yang berumur tujuh belas tahun, mulutmu cukup pintar menfitnah.” Balasan itu membuat Liam seketika menoleh dengan dahi yang berkerut samar.
“Tidak usah menyangkal, gue punya bukti.”
“Haha, bukti sebatas omongan orang. Apa yang perlu dibanggakan,” timpal Arun. Ucapannya keluar begitu santai, seolah-olah rasa bersalah sama sekali tak melekat pada omongannya barusan.
Entah kenapa keadaan bisa dengan cepat berbalik. Kini Liam seolah-olah dibuat geram oleh Arun.
“Orang brengsek tidak akan menyebut dirinya brengsek.” Liam kembali menyerang Arun dengan ucapannya.
Arun menoleh pada Liam. Segurat ekspresi amarah bertengker di wajahnya.
“Lo pikir intuisimu hebat? Tidak usah berucap banyak untuk hal yang lo sendiri tidak tahu.” Liam terdiam. Menyerang balik pandangan sinis pada Arun.
“Last, jangan bersikap peduli.” Arun menekan ucapannya, dan kalimat itu terdengar begitu dingin menghantam gendang telinga Liam.
Sedetik setelahnya Arun langsung mengambil langkah. Menerobos hujan masih lebih baik ketimbang harus berada di tempat yang sama bersama Liam. Meninggalkan Liam seorang diri yang masih menyimpan pandangan kesal dalam matanya.
℘℘℘
“Jadi, bagaimana?”
“Pendekatan dinyatakan gagal,” ucap Liam dengan smartphone yang menempel di telinga kanannya sembari melangkah menuruni anak tangga.
“Tidak di respon?”
“Direspon, hanya saja tidak seperti yang diekspetasikan.” Liam menyadarinya, ada helaan napas panjang di seberang sana.
“Hmm, situasinya lumayan buruk. Tapi jangan berhenti, setidaknya biarkan dia tahu kalau kamu ada usaha. Untuk apa yang akan dilakukannya nanti itu urusan belakang.”
“Lo sendiri tahu kan, sabar juga ada batasannya,” timpal Liam, yang kini bergerak mengambil sebotol minuman bersoda dari dalam kulkas, sebelum akhirnya melangkah lagi dan menyender di salah satu kabinet dapur.
“Ya, kamu tahu sendiri, terkadang sabar harus dipertaruhkan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan.” Gadis di seberang sana meyakinkan Liam, dan laki-laki yang kini hanya memakai kaos putih polos itu hanya menyambutnya dengan sebuah helaan napas frustasi.
“Bisa nggak, kamu lebih perjelas apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Arun. Terus terang, aku masih belum ada gambaran,” gadis di seberang sana kembali meminta. Tarikan napas kembali terlihat dilakukan Liam kemudian. Setelah meneguk minuman yang sedari tadi dipegang, ia mulai kembali membuka mulut.
“Untuk apa yang sebenarnya terjadi, gue masih belum tahu. Lo tahu sendiri kan, sebelum ini gue dan Arun baik-baik saja, ya lo tahu dia itu sepupuku. Tapi, sebulan yang lalu, sikapnya seratus delapan puluh derajat berubah. Sabtu siang, kita udah bikin janji, hangout bareng. Tapi.” Liam menjeda ucapannya sejalan dengan botol minuman yang ditaruhnya di atas kabinet. Gadis di seberang bergumam kecil menunggu kalimat penjelas.
“Entahlah, sewaktu gue jemput, sikapnya bener-bener dingin. Bahkan tanda-tanda untuk bersuara saja tidak ada. Gue bertanya, dan hanya hantaman keras sebagai jawabannya. Singkat kata, dia membenciku, dengan alasan yang bahkan sampai sekarang masih tidak jelas. Dan gue rasa, ini bukanlah hal yang sepele,” sambung Liam kemudian menghela napas, gadis di sana juga ikut menghela.
“Setidaknya akan lebih mudah, kalau dia membuka diri.”
“Andai saja.”
“Bagiamana dengamu?”
“Bagaimana apa?”
“Maksudku, kamu ikut membencinya?”
“Sedang kuusahakan untuk tidak.”
“Untuk bagaimanapun, dia itu sepupumu.”
“Yang membenci sepupunya sendiri tanpa alasan yang jelas,” tambah Liam. Gadis di seberang sana terus saja memberi helaan napas panjang.
“Besok aku sampai di sana, kita teruskan saja besok. Sebentar lagi aku sampai di bandara.”
“Baiklah, hati-hati.”
Liam mengacak surai hitam pekatnya frustasi begitu sambungan panggilan berakhir. Memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Arun dan dirinya sudah cukup membuat kepalanya seolah berputar-putar di tempat yang sama. Seharian ini memikirkannya, tak menutup kemungkinan ia mendapat jawabannya.
Baru saja hendak meneguk minuman bersodanya lagi, atensi Liam terlanjur terusik dengan suara smartphone yang tiba-tiba saja berbunyi, tanda ada pesan masuk.
Liam kembali membuang napas panjang. Barusan adalah pesan dari Ayahnya. Isinya tak lebih adalah pemberitahuan jika beliau tidak akan pulang malam ini. Rumah sakit lebih membutuhkannya yang jelas.
Liam bergerak menjatuhkan bokongnya pada salah satu kursi di samping meja makan yang tidak terlalu jauh darinya. Pelan-pelan tangannya bergerak memijiti bagian belakang lehernya yang kini mendadak nyeri. Mungkin saja karena banyak pikiran. Yang jelas, sepertinya dia butuh istirahat.
Begitu tangan kanannya merabah sesuatu yang familiar di bagian pangkal lehernya, ia sempat terdiam beberapa saat. Mengambil pandang pada salah satu lemari piring kaca yang tak jauh di hadapannya dalam detik berikutnya. Mendapati sosok dirinya yang samar-samar terpantul, membuatnya intens memerhatikan. Ia bisa melihat, luka jahitan yang melingkari pangkal lehernya. Entahlah, perasaannya selalu tak enak ketika melihatnya di pantulan kaca.
℘℘℘
Hari makin ditelan malam. Jam di pergelangan tangan sudah menunjuk pada pukul dimana Gina harusnya bisa terlelap di ranjang putih super empuk miliknya. Lima menit lagi tepat pukul dua belas malam, tapi Gina harus tetap terjaga. Hari ini masih dalam suasana weekend, dan saat itulah jadwal Gina harus bertugas. Dia tak pernah menyangka, menjadi kasir di sebuah convenience store terasa seberat ini. Setidaknya tiga puluh menit lagi jadwal tutup, dan dia harus bertahan sebentar lagi.
Gina melepaskan masker hitam yang sudah dipakainya sejak mulai bertugas tadi, diikuti sebuah mulut yang menguap. Perasaan ragu sempat menghampirinya perihal tindakannya untuk melepas masker, namun ketika merasa situasi cukup aman dan tak ada lagi orang yang berlalu lalang di depan toko akhirnya ia memutuskan untuk melepasnya.
Beberapa petugas yang lain sibuk merapikan beberapa barang yang berantakan, dan juga sebagian sibuk memeriksa beberapa barang lainnya di gudang belakang. Hanya Gina seorang yang kini berada di meja kasir.
Baru saja hendak menguap lagi, tapi Gina sedikit tersentak ketika melihat ada pelanggan yang tiba-tiba masuk semalam ini.
“Selamat datang,” ucapnya ramah. Meski suara itu lumayan terdengar lelah.
Laki-laki berhoodie hitam itu tak menghiraukannya dengan terus melangkah masuk menuju rak berisi berbagai macam mie. Namun dikala laki-laki itu melangkah, mata Gina secara otomatis mengikutinya. Dan tepat didetik setelahnya, Gina menyadari jika wajah laki-laki itu terlihat familiar. Entahlah, dia tidak tahu siapa nama dari pemuda itu, yang jelas ia pernah melihatnya di sekolahnya. Singkat cerita, pemuda itu satu sekolah dengannya. Tapi tetap saja, Gina tidak begitu mengenalnya, karena jujur saja Gina bukanlah tipikal yang suka bergaul di sekolah.
Tak lebih dari lima menit untuk laki-laki itu kembali lagi pada meja kasir dengan membawa sebuah cup mie pedas, sebatang keju morazella, dan sebotol susu kedelai dingin.
“Suka sesuatu yang pedas?” tanya Gina. Ada dua alasan kenapa dia bertanya. Pertama, sebatas basa-basi, semacam formalitas belaka bersikap ramah pada pelanggan. Kedua, menarik atensi pemuda itu yang sejak tadi tak menatapnya.
Pemuda itu mendongak. Dilihat dari reaksi matanya yang sedikit melebar, Gina dapat menarik fakta, jika laki-laki itu sama terkejutnya menyadari presensi Gina.
“Ternyata kita satu sekolah,” tambah gina dengan senyuman sembari menghitung belanjaan laki-laki tersebut.
Arun tak menyangka menemui gadis itu di sini. Jadi sekarang dia berubah profesi menjadi kasir? Dia sempat skeptis tentang pertemuan yang cenderung sangat kebetulan ini. Tidak ingin menampilkan reaksi berlebih, Arun hanya tersenyum simpul.
“Semuanya dua puluh ribu.” Gina menyerahkan kantong belanjaan sang pemuda sembari berucap.
Arun menyerahkan uang pas, lalu meraih kantong belanjaannya dengan segera. Senyuman ringan menjadi balasan pada ucapan Gina barusan.
Dahi Gina sempat berkerut samar, menyadari akan respon sang pemuda yang tak ingin membuka suara. Menilik ke wajahnya sepertinya dia tipikal orang yang pendiam, meskipun tak masuk akal menarik kesimpulan hanya dari wajahnya saja.
Arun melenggang pergi, tetapi dia berhenti di ambang pintu. Terlihat sempat bergelut dengan monolog batin yang dibuatnya. Perlahan ia melangkah masuk, menghampiri Gina yang kini melemparnya dengan pandangan tak mengerti.
“Apa ini buka dua puluh empat jam?” Satu-satunya suara yang keluar dari mulut Arun.
“Maaf, kami tidak buka dua puluh empat jam,” balas Gina. Senyuman ringan masih terlampir di wajahnya.
“Sebentar lagi ditutup?” tanya Arun kembali. Gina bergumam pelan, menimbang-nimbang.
“Memangnya kenapa?”
“Kalau boleh, aku ingin sekalian makan mienya di sini, tapi aku pikir ini sebentar lagi akan ditutup,” jawab Arun. Ada segurat harapan jika toko ini mungkin saja menunda waktu tutupnya sebentar lagi.
“Sebenarnya tiga puluh menit lagi kami akan tutup. Tapi kalau ingin makan di sini juga tidak apa-apa. Kalaupun lewat dari tiga puluh menit, kami akan menunggu. Pelanggan lebih diutamakan,” timpal Gina. Arun sempat menghela lega sebelum akhirnya kembali berucap “Terimakasih.”
Arun melangkah pelan pada eat area, memilih meja paling ujung dekat microwave sebagai tempatnya. Tak menunggu waktu lagi, ia langsung segera membuka bungkus cup mie dan menyeduhnya dengan air panas yang sudah di sediakan. Tidak lupa, juga menaruh keju diatas mie dan dimasukannya ke dalam microwave selama tak lebih dari semenit.
Arun terpaksa memakannya langsung ditempat. Satu hal yang pasti, dia tidak akan menyantapnya di rumah. Jika kalian bertanya kenapa, dia punya satu jawaban. Dia benci rumah.


 Ditnata
Ditnata
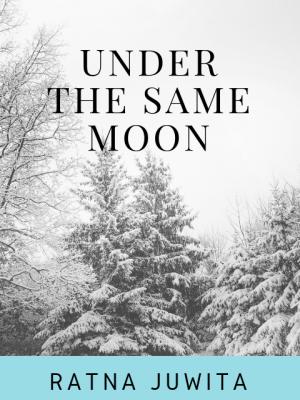
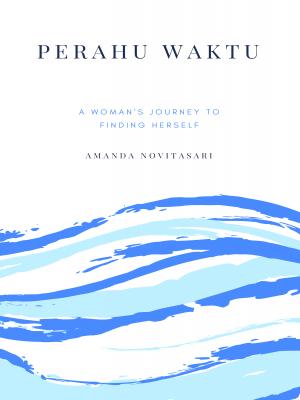








@Ditnata sama2. Ditunggu next chapternya ya. Oh iya, mampir juga dong di ceritaku. Hehe.
Comment on chapter Prolog