Episode 2
Setelah pengalamanku sore itu, di Kampung Kramat bersama Lukman. Serta kejadian nahas, dengan robohnya rumah si Mbah Suro sang dukun. Aku kembali dihadapkan masalah rumit dengan Satria. Berkali-kali ia menghubungi, tetapi selalu mengabaikannya. Bahkan sampai ia mengirimkan pesan singkat, yang intinya permintaan maaf atas perasaannya terhadap Kartika.
Sore itu, setelah dua hari berlalu dengan kejadian mistis bersama Lukman. Di dapur tempat kerjaku di hotel. Selepas berbenah, taman belakang. Dengan penuh keyakinan, aku hubungi salah satu sahabat bernama Teguh di Bandung yang pernah menawarkan pekerjaan di sana. Berharap masih ada kesempatan dari tawarannya untuk bekerja di sana.
“Halo, Guh. Gimana kabarnya?” sapaku begitu telepon dijawab oleh Teguh.
“Halo, Bim. Alhamdulillah baik, Bim. Gimana nih, rencana pindah kerja ke sini? Jadi enggak? Mumpung masih ada kesempatan, lho!” balas Teguh terdengar dengan nada suaranya yang semringah, langsung menanyakan niatku tadi.
“Baru mau nayain masalah itu, Guh. Hehehe.” Aku tersenyum dengan ungkapan sahabatku itu.
Memang Teguh ini orangnya tanggap dan supel, kalau aku menghubunginya. Tidak jarang juga saat dulu sering main ke Bandung, meski sekedar liburan cuti. Ia mengajakku keliling kota, memperkenalkan makanan khas juga tempat hiburan yang cocok untuk liburan keluarga.
Teguh ini salah satu sahabatku sejak kecil, begitu pun dengan Satria. Namun aku lebih dekat dengan Teguh, ketimbang dengan Satria. Sebab jarak rumah kami di kampung, tidak begitu jauh. Sewaktu kecil, selain belajar ilmu bela diri dari kakekku. Kami sering main detektif-detektifan. Satria yang sering jadi polisinya, sementara aku dan Teguh jadi penjahatnya. Meski hanya sekedar permainan, hal itu sangat mendekatkan hubungan kami sebagai sahabat.
Pernah suatu hari kami berkelahi dengan anak desa tetangga, karena sering dihina atau dipalaki mereka. Mungkin, karena cuma aku yang bisa dikatakan mahir bela diri saat itu--meski enggak terlalu mahir juga kayak Jet Li pemain film laga. Sehingga akhirnya bisa mengalahkan mereka, meski kalah jumlah dan muka setengah babak belur. Namun malah kami yang kena damprat, dari aparat desa juga keluarga karena bikin onar dan membuat malu keluarga saat itu. Sampai akhirnya harus terpisah, saat mulai masuk bangku kuliah. Aku dengan Satria, satu jurusan di kampus teknik komputer. Sementara Teguh, lebih memperdalam ilmu menejemen bisnis perbankan di Bandung.
Sekelumit kenangan masa lalu, membuatku termenung ketika sore itu menelepon Teguh. Seakan-akan ia tahu masalahku saat ini, suaranya di telepon menyadarkanku, “Woy! Malah ngelamun! Kamu lagi ada masalah, Bim? Coba ceritain, siapa tau aku bisa bantu.”
“Ah eng—enggak, Guh. Yah biasalah, orang hidup pasti ada masalah.” Aku mencoba menutupi masalahku dengan Satria, bermaksud agar Teguh tidak ikut membenci sahabatnya juga. Biarlah, cukup aku yang merasakan pengkhianatan seorang sahabat. Jangan sampai sahabatku yang lain, kena imbasnya.
“Kalau kamu enggak ada masalah, pasti nadanya beda, Bim. Aku tau kamu dari kecil kayak gimana.” Kembali suara Teguh menyadarkanku, dengan lamunan masalah yang semakin membuatku lemah.
Ah udahlah, entar kalau udah di sana aku cerita. Sekarang, gimana rencanaku buat kerja di sana, bisa enggak?” tanyaku kembali, bermaksud mengalihkan pembicaraan.
“Ya, kalau aku sih tergantung kamu siapnya kapan, Bim. Kemarin temanku, yang kerja di Telekom nanyain lagi, kapan kamu ke sini. Seenggaknya wawancara aja dulu, mengenai sistematis kerjanya gimana. Baru kalau kamu siap, bisa langsung kerja di sini. Aku bisa jamin, kamu langsung kerja kok, Bim.”
“Ouh gitu? Ya udah, besok deh aku berangkatnya. Sekarang mau izin dulu ke atasan, biar entar kalau diterima di sana bisa langsung ngasih surat pengunduran diri.”
“Sip kalau gitu, Bim. Aku tunggu kedatanganmu, ya?”
“Oke, Guh.” Telepon pun segera kumatikan. Belum sempat beranjak dari dapur. Muncul Lukman, yang sedari tadi memerhatikanku menelepon.
Dengan mimik muka serius, layaknya seorang paparazi yang sedang memburu berita para selebriti, Lukman pun bertanya, “Kamu serius mau ninggalin hotel ini, Bim? Apa gara-gara si Kartika itu?”
“Eh kamu, Luk. Aku kira enggak ada orang. Kamu denger percakapanku, sama sahabatku tadi ya, Luk?”
“Enggak juga, Bim. Ini mau bikin kopi, enggak sengaja denger percakapanmu tadi. Emang kenapa, sampai kamu harus keluar kerja di sini, Bim? Apa kurang puas, sama gaji di sini? Atau ada penawaran baru, buat kerjaan lebih layak dari sini?” tanya Lukman, sambil mengisi gelas miliknya yang berisi kopi di tempat dispenser dekat wastafel dapur.
“Yah rencananya gitu, Luk. Kamu tau sendiri, gajiku di sini berapa? Sementara aku terus didesak Kartika, buat ketemu keluarganya. Kalau mereka tau kerjaanku kayak apa, pasti bakal jadi masalah yang lebih serius entarnya. Seenggaknya ada sedikit perubahan, buat nyari impianku sebagai teknisi komputer di sana.”
“Ya bagus, sih. Sayang juga, sama gelar sarjanamu selama ini. Udah kuliah tinggi, malah dapet kerjaan kayak gini. Meski enggak terlalu hina juga sebagai Office Boy, seenggaknya kuliahmu ada manfaatnya juga, ya?”
“Enggak juga, Luk. Sebenarnya aku bersyukur masih bisa kerja, meski kayak gini keadaannya. Tapi bukan itu masalahnya, Luk. Ada hal lain yang ingin aku capai, sebelum entar siap buat nikahin Kartika. Itu pun, kalau jadi ama dia.”
“Lho! Emangnya kenapa, dengan hubunganmu ama Kartika, Bim?”
“Panjang ceritanya, Luk. Enggak bisa cerita sekarang. Aku mau nemuin dulu Bu Neni, ya? Buat izin beberapa hari. Entar pulang dari Bandung, aku cerita, deh.” Aku pun segera berbenah mengganti pakaian kerja, sebelum bos hotel pulang setelah melihat jam dinding di dapur hampir mendekati jam empat sore. Sebab biasanya, sang bos pulang sekitar jam segitu. Sementara Lukman, masih asyik dengan kopi di tangannya.
“Ya udah, kamu hati-hati aja di sana. Aku juga sering ke Bandung sih, main ke rumah temen. Tar kalau jadi pindah, jangan lupa sama aku di sini, ya? Hehehe. Minta alamatnya juga, kalau kamu jadi pindah ke sana, ya? Siapa tau pas aku main ke sana, bisa mampir ke tempatmu.”
“Hahaha siapa lagi yang bakal ngelupain kamu, Luk. Cowok mistis yang enggak pede ngadepin cewek, akhirnya nanya sama Mbah yang malah mati mengenaskan. Hahaha.”
“Sialan kamu, Bim. Bisa aja ngeledeknya. Hahaha!”
“Kalau jadi pindah, aku kasih alamatnya, deh. Oke? Entar aku siapin surat pengunduran diri, kalau ada kabar dari sana, ya? Tolong kamu kasih ke Bu Neni.”
Lukman hanya mengacungkan jempol kirinya ke arahku, sambil menyeruput kembali kopi di tangan satunya. Aku pun beranjak dari ruang dapur. Meninggalkan Lukman yang selalu asyik dengan kopi, kalau sudah mendekati jam pulang kerja. Perlahan langkahku terhenti, di depan sebuah ruang kantor bertuliskan ‘Pimpinan Hotel’. Berharap bos masih ada, dan memberi izin beberapa hari untuk pergi ke Bandung.
*****
Setelah sore itu mendapat izin dari Bu Neni, bos hotel. Aku segera pulang, dan berbenah untuk persiapan esok berangkat ke Bandung setelah menitipkan surat pengunduran diri kepada Lukman. Dengan motor matik warna hitam kesayangan, aku pun berlalu meninggalkan bangunan yang selama ini telah menopang segala kebutuhan hidup.
Setengah jam berlalu. Aku pun sampai di rumah tua bercat putih dengan corak zaman dulu, tempatku berteduh selama ini. Seakan-akan berat untuk kutinggalkan dengan rencana kepindahan ke Bandung.
Ribuan kenangan singgah di rumah tua itu, ketika kedua orang tuaku masih ada. Walau kini mereka sudah tiada sejak aku masuk kuliah semester empat, tiga tahun yang lalu, karena peristiwa tragis saat pulang pasca menunaikan ibadah haji. Sementara adikku satu-satunya tinggal di Sukabumi, bersama bibi. Sebab saat itu, belum bisa membiayai sekolah untuknya. Akhirnya segala sesuatu harus kukerjakan sendiri, termasuk mencuci baju, berbenah rumah, sampai mencari makan di warung dekat pertigaan kampungku.
Yah, begitulah nasib anak yang ditinggal kedua orang tua, harus bisa mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Setidaknya masih bisa mencari sesuap nasi, tanpa belas kasihan orang.
Beberapa stel baju, aku lipat dan memasukkannya ke tas ransel warna abu-abu, yang biasa kupakai kalau hendak bepergian. Ijazah kuliah, termasuk sertifikat nilai kompetansi di bidang komputer diselipkan di antara lipatan baju.
Sejenak kupandang deretan foto yang berbingkai tua, di atas lemari televisi. Terlihat kebahagiaan, saat kedua orang tua masih ada. Begitu pula wajah cantik adikku bernama Riani, yang saat ini mungkin sudah masuk dunia perkuliahan. Ah ... sudah satu tahun aku tidak menemuinya. Ada semburat rasa rindu, jika sudah melihat senyumnya yang mengembang.
“Dek, sudah lama kita enggak ketemu. Gimana kabarmu di sana, ya?” lirihku, sebelum beranjak tidur.
Segera kuambil ponsel dan mencari nomor bibi, bermaksud menghubunginya sebelum keberangkatanku esok ke Bandung. Belum sempat menekan nomor ponsel bibi, tiba-tiba Kartika menelepon. Ada rasa enggan sebenarnya, untuk menerima telepon darinya. Sebab teringat apa yang Satria katakan tempo hari, perihal hubungan mereka. Tetapi, kalau semakin menjauh tanpa ada kejelasan.
Ada rasa takut juga, kalau hanya penilaian sepihak perihal masalah ini. Setidaknya dengan adanya penjelasan sedikit dari Kartika, mengenai masalah kami itu. Bisa sedikit memberikan kesegaran dalam otakku, sebelum pindah kerja nantinya.
Meski sedikit ragu, akhirnya kuterima telepon yang berdering dari Kartika. “Assalamu’alaikum, Kartika. Ada apa hubungi aku?”
“Wa’alaikumsalam, Bim. Kamu ke mana aja, sih?! Bisa kita ketemu malam ini? Ada hal penting yang ingin kubicarain!” pinta Kartika, terdengar suaranya sedikit emosi.
“Hal apa yang mesti kita bicarain, Tik? Aku ....”
“Pokoknya penting! Aku enggak mau ada alasan, atau kita pisah!”
Deg! Mendengar keinginan Kartika yang mendesak dengan nada ancaman seperti itu, membuatku mau tidak mau harus menuruti keinginannya untuk bertemu. Dengan perasaan malas, akhirnya aku pun keluar rumah menemuinya ke sebuah taman kota tempat biasa kami menghabiskan waktu saat masih bersama.
Suasana malam kota Cirebon, sudah seperti layaknya kota besar yang hampir tidak pernah mati. Hilir mudik kendaraan yang mengantar para pemburu mimpi, entah yang baru pulang kerja ataupun yang baru tiba ke kota udang ini, sudah merupakan pemandangan biasa bagiku.
Di sebuah stasiun kota, dekat dengan taman alun-alun Kejaksan. Tampak ramai oleh penjaja makanan khas kotanya para wali ini yaitu Empal Gentong. Tenda pedagang Sega Jamblang di emperan trotoar, di mana nasi yang dibungkus daun jati dengan menu lauk yang bisa dipilih sendiri layaknya prasmanan, di antaranya telur puyuh balado, sambal goreng, daging dendeng, telur dadar atau masakan khasnya ikan asin, tempe goreng juga sayur tahu serta aneka menu lainnya, yang menggoda siapa saja yang mampir di kota yang berjulukan Kota Udang ini.
Dengan mengayuh sepeda, kutelusuri deretan tenda makanan tadi yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dulu, saat terjadinya peristiwa pembangunan jalan raya antara Anyer ke Panarukan oleh penguasanya bernama Daendels di zaman penjajahan dulu.
Memasuki gerbang alun-alun kota. Sorot mataku menelusuri sosok wanita yang mengenakan kemeja Vintage warna putih berenda di bagian depannya, juga celana jins cutbray long pants warna hitam ala gadis tahun 90-an, tiada lain adalah Kartika, wanita yang selama ini mengganggu kehidupanku.
“Sudah lama nunggunya, Tik?” sapaku begitu mendekati Kartika, seraya menuntun sepeda mendekatinya. “Baru pulang kerja?”
“Yah ... begitulah,” jawabnya sedikit acuh. Tampak guratan rasa kecewa di wajahnya yang ayu itu.
“Ada hal apa yang ingin kamu bicarain?” tanyaku seraya duduk di sebuah teras depan alun-alun, setelah menaruh sepeda.
“Seharusnya aku yang tanya, ada apa sama kamu selama ini? Kenapa susah dihubungi?” ketus Kartika kemudian duduk di sampingku, meski wajahnya terlihat dingin.
“Enggak ada apa-apa, Tik. Aku hanya pengen menenangkan diri aja, enggak lebih.”
“Emangnya kenapa mesti menenangkan diri, tanpa mau ngehubungi aku? Bukannya selama ini, antara kita enggak ada masalah, kan? Apa jangan-jangan ... gara-gara aku desak kamu buat nemuin keluargaku, gitu?!”
“Enggak, bukan begitu. Kamu ... ah, sudahlah! Aku lagi enggak mau ngebahas masalah ini.”
“Kamu jangan picik gitu dong, Bim! Cuma gara-gara aku desak kamu buat nemuin keluarga, jadinya malah ngehindar gini. Itu namanya pengecut, tau?!”
“Enggak, bukan itu masalahnya. Kalau cuma mengenai ketemu keluargamu, aku udah bilang, kan? Kalau aku siapnya setelah ada kerjaan mapan, selain kerjaan yang sekarang. Ini perihal ..., kamu ingat Satria, kan?” Aku terdiam sejenak, seraya menatap wajah Kartika yang terpancar cahaya bulan malam itu.
“Satria?! Kenapa dengan dia, Bim?! Kamu mau sangkut pautkan, masalah kita sama dia?” Tampak Kartika terkejut dengan ucapanku tadi. Sementara aku hanya bisa tertunduk, sedikit menyesali apa yang baru saja terlontar dari bibirku.
“Kamu sama dia ada ... eee.” Aku kembali terdiam, tidak ada keberanian untuk mengatakan perihal apa yang Satria katakan tempo hari.
“Ada hubungan, gitu?” potong Kartika, “satu hal yang mesti kamu tau ya, Bim! Antara aku sama Satria, enggak ada hubungan apa pun seperti yang kamu kira! Kalau pun niat dia, buat jadiin aku istri. Itu semua tergantung kamunya, mau gimana terhadapku. Bisa saja aku terima keinginan dia. Tapi enggak semudah itu menggantikan kamu, yang selama ini udah hadir dalam hidupku. Aku sama dia, cuma pengen ada kejelasan dari kamu, perihal apa yang diniatkan buat nikahin aku. Suatu saat, kamu pasti ngerti apa yang terjadi ini!”
Tiba-tiba Kartika beranjak meninggalkanku di teras alun-alun, dengan perasaan tidak menentu. Aku segera bangkit dan berusaha mengejar langkahnya, namun dia menolak dan tetap berlalu sampai membaur dengan keramaian jalan, kemudian memasuki sebuah angkutan kota. Aku berusaha berbicara kepadanya di luar angkot tersebut, namun ia tetap diam menyimpan sebuah kekesalan yang kubuat malam itu, hingga kendaraan itu pun berlalu membawanya pulang.
Aku yang terdiam melihat Kartika pergi, hanya bisa merutuki apa yang kualami malam itu dengan berbagai pertanyaan di hati. Apa yang dimaksudnya itu? Apa perkiraanku selama ini, terhadap dirinya sama Satria adalah salah? Atau ada hal lain, yang sama sekali tidak aku ketahui? Ah ... sungguh membingungkan. Setidaknya aku tahu satu hal, kalau Kartika masih menyimpan rasa sampai nanti saatnya, aku memberanikan diri untuk melamarnya.
Setelah pertemuan dengan Kartika di alun-alun kota, aku segera kembali pulang dengan mengayuh sepeda meski pikiran kalut. Sesampainya di rumah, aku mencoba memejamkan mata walau masih menyisakan kegundahan, yang selalu mengganggu pikiran. Hingga akhirnya aku pun terlelap, melupakan sejenak masalah yang sedang kuhadapi saat ini.
*****


 Kang_Isa
Kang_Isa






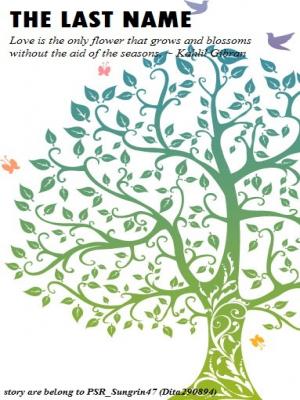





@AjengFani28 Terima kasih sudah mampir, ya. Untuk sementara cerita ini aku posting di platformnya Storial.co, Mba. Lagi diikutkan dalam kompetisi novel. Nanti aku posting keseluruhannya, setelah ada kabar di sana, ya. Untuk karyaku yang sekarang sedang proses di sini, judulnya "IMPIANKU". Kalau berkenan, mampir juga di sana, ya. Terima kasih sudah mampir. :)
Comment on chapter Episode 1Salam semangat selalu. :)