Sajak adalah kawan kita, akhirnya.
Pisau itu telah selesai membunuh, kemarin.
Tapi siapa yang tahu? Tak ada.
Sajakmu, sajakku, lahir kembali.
Hari ini aku duduk pada sebuah bangku di beranda, dengan sebatang pena di tangan dan selembar kertas di atas meja. Aku memandang ke arah depan. Di hadapanku, di bawah teduh pohon beringin itu, Arila–istriku–sedang mengenakan baju putih dengan kerudung yang sama putihnya. Ia mengayunkan ayunan yang sedang diduduki Raina–anak gadis kami.
Aku pernah ingat pagi seperti ini: dahulu, aku pernah bermimpi tentang gadis kecil yang naik ke pundakku. Ia sangat suka ketika rambutnya menyentuh sulur beringin. Ia lalu memanggil ibunya yang sedang duduk manis pada sebuah bangku di beranda, “Ibu ... Ibu ... coba lihat aku. Rambutku terasa begitu dingin ketika tersentuh ini.” Di saat itu juga aku melihat selembar wajah ibu itu. Dan terlihat jelas, wajah itu milik Arila.
“Mimpi adalah juga seperti mewakili sebuah takdir,” ucap Arila lima belas tahun yang lalu.
***
/0/
“Mimpi adalah juga seperti mewakili sebuah takdir.”
“Itu sebuah pernyataan yang kamu ucapkan setelah kamu bercerita tentang mimpimu itu. Sebenarnya, apa yang kamu sembunyikan?” sambung Arila.
“Sudah jangan bertanya. Biarkan waktu yang menerjemahkan.”
“Kita masih sahabat. Tapi siapa yang akan tahu hari esok? Sekali lagi, tak ada.”
“Dan jangan menatapku seperti itu. Seorang perempuan berhak membuang tatapan seorang lelaki,” sambungku.
Di sisi tua jembatan itu, ia sambut aku dengan baju hitam lengan panjang, dengan kerudung yang sama hitamnya.
“Lalu, ada apa sebenarnya, pagi-pagi seperti ini kamu mengajakku ke sini?” ia bertanya sambil menatap genangan air sungai.
“Ini novel, teruntuk kamu.”
“Bukankah kita sama-sama manusia?” sambungku lagi.
Kuperhatikan wajahnya yang diam-diam sedikit menoleh ke arahku. Seketika, bibirnya mulai berkembang dan tatapannya kembali ia arahkan ke bibir sungai. Dan pada sebuah jam, pertemuan itu berakhir dengan kata lepas. Bertemu dan lepas, begitulah tatapan berada di antara keduanya.
/1/
“Kenapa seperti ini? Apa yang kurasakan saat ini selaras dengan mimpimu sepekan yang lalu.”
“Kadang, sebuah perasaan bisa datang kapan saja. Simpanlah baik-baik. Ini tak akan lama. Percayalah, jika memang benar mimpi itu mewakili sebuah takdir, kamu hanya butuh diam.”
Sebagaimana kami yang bersahabat–sebagaimana persahabatan yang mengikat manusia, etika persahabatan itu tetap ada. Tapi semua tahu, sebuah perasaan tak mudah untuk dialihkan. Maka kami saling bertukar pendapat tentang persahabatan kami yang mulai dikotori oleh secuil cinta. Persahabatan jadi cinta? Bagiku itu hanya sebuah alasan yang sengaja dibuat oleh sepasang sahabat yang sebenarnya ingin saling bercinta. Tak ada yang murni. Tak ada juga yang kebetulan. Semua manusia pintar dalam hal berpura-pura. Lalu yang terjadi kepada kami? Apakah itu murni? Apakah itu kebetulan?
“Semua berawal dari sajak!” suaraku tegas.
“Ya, sajak. Ia mengantarkanmu ke hadapanku.”
“Bukankah kamu masih ingat, setahun yang lalu kamu datang kepadaku, lalu merengek memintaku untuk membuatkanmu sepotong sajak?”
“Dan berawal dari sana, kamu semakin mendekat. Aku pun semakin mendekat. Dekat dan lebih dekat lagi. Dan akhirnya kita menjadi sepasang sahabat yang sama-sama menyukai dunia sastra.”
“Aku masih ingat betul,” sambungku.
“Ya, benar. Sajak.”
“Tapi jangan lupakan mimpimu itu. Ia adalah penyebab utama!”
“Aku juga masih ingat betul. Dan jangan menatapku seperti itu,” sambungnya.
Kami kembali terdiam cukup lama. Memandangi setiap gerak-gerik air sungai dan burung-burung merpati yang turun satu demi satu di permukaan. Juga sepasang angsa itu yang bermain dengan arus hingga menepi. Di sisi tua jembatan itu, kerap kami bertemu dan saling bertukar sajak.
“Mendung jatuh di kota ini. Barangkali, sebentar lagi, hujan pun akan jatuh,” dan akhirnya ia mengakhiri sebuah pembicaraan.
/2/
Empat tahun berlalu ... kami masih bersahabat. Masih sering bertemu di sisi tua jembatan itu. Ia tetap berteduh dengan kerudung hitamnya. Sedang aku tetap mengenakan celana yang tersobek di bagian lutut. Hari itu, pada sebuah pagi bertanggal 23 September 2007, kami kembali saling bertukar sajak. Seperti biasa, sebelum menuliskan sajak, kami harus menentukan terlebih dahulu, bertema apa sajak yang akan kami tulis.
“Bagaimana jika tentang keberangkatan?” ia melempar saran.
“Keberangkatan yang seperti apa?”
“Ah kamu banyak tanya.”
“Baiklah ... aku mengikuti.”
Orang-orang berlalu begitu saja, melewati kami yang sedang sibuk melempar tatapan ke arah sungai. Merpati-merpati itu seakan ingin menyapa kami. Seakan-akan mereka ingin memberi kesaksian bahwa kami terlalu banyak berdiam.
“Sebenarnya, hari ini aku ingin berpamitan. Aku akan pergi ke luar kota untuk sebuah titah. Ke sebuah kota di selatan sana,” lanjutnya.
Sontak saja dadaku berdegup. Resah karena mendengar pernyataannya. Dan aku sempat berpikir seperkian detik, bahwa aku harus merasa kehilangan sebelum memiliki. Tapi seketika pikiran itu hilang saat mendengar penjelasan dari pernyataan selanjutnya.
“Tenang saja. Aku pasti akan kembali. Sebagaimana kapal yang akan selalu berpulang di pelabuhan sebelumnya.”
“Tapi kamu pun pasti mengerti, dan pelabuhan itu pun pasti mengerti, bahwa setiap kemungkinan itu pasti ada. Barangkali kapal itu butuh berhenti di pelabuhan lain, untuk sejenak merekatkan diri,” balasku.
“Sebagaimana katamu, ‘Siapa yang akan tahu hari esok?’ Sekali lagi, tak ada. Dan sebagaimana katamu lagi, ‘Biarkan waktu yang menerjemahkan’. Aku sudah banyak belajar darimu. Kini, jika memang benar mimpi itu adalah seperti juga mewakili sebuah takdir, maka aku hanya butuh diam.”
Pukul 5 sore itu, langit memasang mendung. Dan angin perlahan-lahan mengantarkan hujan. Di bagian selatan jembatan itu, dengan sebuah payung ia berjalan menjauhi utara. Dan ia berlalu dan menghilang bersama hujan September.
/3/
Seperti halnya sepasang tokoh pada sebuah drama, kami dipertemukan kembali di sisi tua jembatan itu, tiga tahun kemudian. Saat itu, pada sebuah jam, ia datang dengan kembang di tangan. Ia menghampiriku dan tersenyum kepadaku. Barangkali ia ingin mengatakan sesuatu. Atau barangkali, aku yang ingin melemparkan sesuatu. Di senja yang sama pucatnya, jembatan tua itu telah menjadi tempat yang paling nyaman bagi kami untuk saling membunuh rindu.
“Aku pernah kenal senja seperti ini: tentang seorang perempuan yang berjalan ke arah selatan, lalu menghilang.”
“Tapi saat ini, perempuan itu sedang berjalan ke arah lelaki yang menunggu di arah utara,” ia membalas.
Sejak saat itu, kami mulai percaya, bahwa mimpi itu akan benar-benar menjadi sebuah takdir. Tentu, mimpi dapat dikejar. Selama manusia yang bersangkutan tetap berusaha berlari. Dan kami percaya, jika kami saling memahami dan sama-sama berlari ke arah mimpi itu, maka mimpi itu akan menjadi nyata.
“Kamu ingin menunggu percobaan apa lagi?”
“Bukankah dalam lima tahun ini, kita sudah melakukan berbagai macam percobaan?”
“Dan kurasa, kepulanganku ini adalah percobaan yang terakhir,” sambungnya.
“Menikah tak segampang menulis sajak.”
“Sekali lagi, kamu hanya butuh diam.”
“Kita, bukan hanya aku.”
Di sisi tua jembatan itu, senja seakan ingin pergi begitu saja. Tapi bulan seakan melambat. Dan untuk waktu yang serba sedikit itu, kami harus kembali berdamai dengan kata lepas.
/4/
22 Februari 2011, di tempat duduk pengantin itu, akhirnya kami menikah. Ia duduk di sampingku, menggenggam erat tanganku sambil berbisik, “Mimpimu benar-benar menjadi takdir.” Aku hanya tersenyum menatap sepasang mata itu. Seorang Hawa–sebuah karya Tuhan–yang hadir dalam mimpiku enam tahun yang lalu, telah resmi menjadi istriku. Lalu aku membalas bisikan itu, “Dan aku tidak bisa berkata apa-apa.”
“Aku ingin berumah di bawah teduh pohon beringin. Karena aku adalah bagian dari mimpimu, maka aku ingin mimpimu itu mencapai titik sempurna,” bisikmu lagi di sela-sela ramainya para tamu.
Acara pernikahan kami berlalu begitu saja. Sampai pada suasana yang begitu sepi, perlahan-lahan kami meninggalkan tempat duduk pengantin itu. Kemudian perlahan-lahan Arila masuk ke dalam sebuah kamar. Saat aku menyusulnya, di ambang batas pintu itu, sejenak aku berhenti karena mendengar suara bisikan di belakangku. Terdengar perlahan namun begitu jelas, “Ini adalah sebagian dari takdirmu. Tapi mimpi itu belum selesai!” Aku terperangah. Sontak aku menoleh ke belakang. Aku melihat sepasang sayap membentang di punggung seorang pria. Lalu pandanganku kabur terkena cahaya yang begitu menyilaukan. Seperkian detik kemudian, pria itu sudah menghilang ....
***
Di beranda ini, aku menulis sebuah cerita. Sebungkus cerita yang akan menjadi hadiah untuk istriku, Arila. Lembaran cerita ini akan aku selipkan pada buku hariannya–di halaman terakhir tempat ia biasa menuliskan sajak. Dan pada sebuah penulisan di kalimat terakhir, tiba-tiba lamunku pecah begitu saja. Aku melihat Raina sudah berada di sampingku, menatapku, dan dengan suara lantang ia berkata:
“Ayah ... Ayah ... Hari ini Ibu ulang tahun kan? Kenapa Ayah diam saja di sini?”
“Ayo, Yah ... segera letakkan bunga ini di atas rumah Ibu. Sudah sejak tadi Ibu menunggu di bawah pohon beringin itu.”
Semua takdir selalu berbicara tentang kematian.
Dan kita, akan lahir kembali. (*)


 AlifFebry
AlifFebry
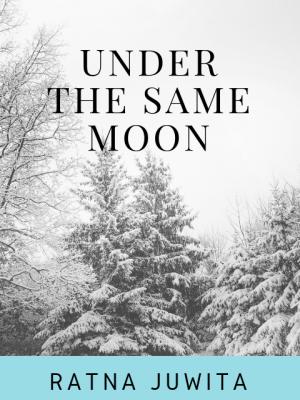



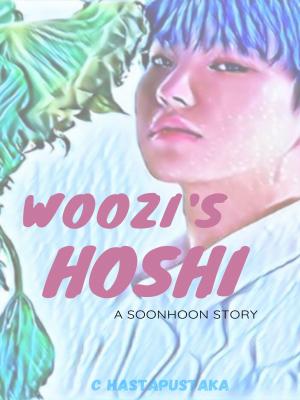


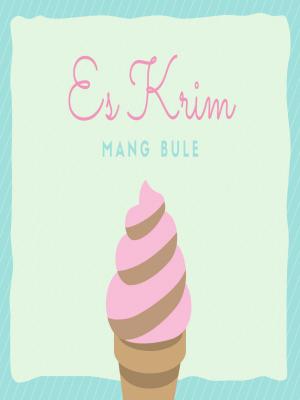


Cerita ini juga pernah ada sekaligus menjadi pemenang di yangpaling.com, kan?
Btw, selamat ya. Dan ya, ending dari cerita ini tidak terlalu terduga. Penutupan yang apik.