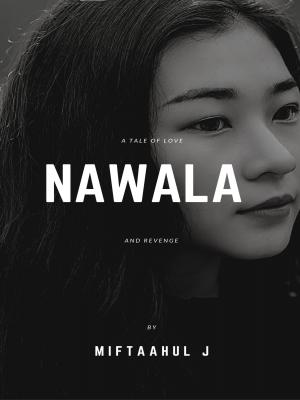Awal hari yang muram . Awan menggantung tebal memenuhi ruang-ruang langit Kota Berlin, siap menumpahkan miliaran kubik air ke seluruh penjuru bumi Adolf Hitler itu. Angin berhembus penuh semangat, mencengkeram kulit. Aku membetulkan posisi kerudung agar lebih nyaman, sesekali melihat G-Shock yang melingkar manis di pergelangan kiri. Huufh…sampai berapa lama aku membusuk di halte ini? Tak biasanya terjadi di Berlin. Kota yang berani sesumbar memiliki sistem transportasi terbaik di dunia..
“Nadia..” seorang pria berambut coklat menyapaku ragu-ragu. Wajahnya terlihat pucat dengan senyum tipis , dan syal berwarna jagung. Ia mengenakan sweater kelabu kusam bergaris kuning. Usianya mungkin sebaya denganku. Atau lebih tua sedikit. Aku tak yakin. Tapi satu fakta yang tak terbantahkan : Dia tampan!
“ Maaf? Apa saya mengenal Anda?” tanyaku ragu-ragu, sambil mengernyitkan kening, mencoba mengumpulkan serpihan memori yang terserak di cerebrum-ku.
“Heinrich..Heinrich Schaum. Kita sekelas di kelas Sejarah…” ujarnya bersemangat. Tangannya yang bersarung tangan diulurkan padaku. Aku manyambutnya. Terasa hangat.
“Oh.” aku hanya ber ‘oh’ saja. Wajahnya sama sekali tak muncul dalam database otakku. Semakin keras aku mencoba mengingat, semakin bias bayang-bayangnya. Entahlah. Terlalu banyak yang harus kuingat. Begitu banyak wajah asing yang kukenal di negeri ini. Semua terlihat sama. Sayangnya wajah pria ini tak terekam dengan baik dalam memoriku.
“Tak biasanya bus terlambat…” keluhnya.
“Yah..sangat jarang terjadi” Jawabku sambil melihat di sekitar halte. Banyak manusia-manusia jangkung bergerombol menunggu bus bernomor 100. Maklumlah, siapa yang tidak tahu bus jurusan Zoologischer Garten – Alexanderplatz ini? Bus favorit para turis yang berkunjung ke Berlin karena melewati obyek-obyek wisata terkenal di kota ini. Dua tahun lalu, tepatnya saat musim dingin, aku mendaratkan kakiku ke daratan Eropa untuk melanjutkan kuliah S2. Aku mendapat program beasiswa yang kuidam-idamkan. Kupikir aku sangat beruntung. Hanya beberapa gelintir mahasiswa Indonesia yang bisa demikian. Apalagi aku. Siapa sangka kalau Nadia Rahmawati, putri guru swasta yang gajinya segelintir, dari desa tertinggal di pelosok Jombang bisa merasakan kuliah di negeri Jerman ini? Alhamdulillah.
“Ayo naik..” ajak Heinrich membuyarkan lamunanku. Rupanya bus yang kami tunggu-tunggu sudah tiba tanpa aku sadari. Tanpa menunggu dua kali, segera aku menaiki bus. Penumpang mulai penuh. Wajah-wajah tanpa ekspresi bertaburan, tak peduli. Heinrich duduk di sebelahku, seraya berceloteh mengenai apa saja yang dilihatnya. Tentang cuaca yang tak bersahabat, tentang bus yang jalannya terlalu lambat, sampai harga mobil keluaran Mercedes-benz yang harganya melangit. Aku tak begitu tak tertarik mendengar ceritanya. Aku lebih sibuk memikirkan isi email dari Mbak Murni, kakakku yang tinggal di Solo. Dia mengabarkan kalau minggu depan mungkin Ibu akan menjalani operasi batu ginjal. Ada semacam batu teramat kecil yang menyumbat kalkulus urinernya sehingga menyebabkan infeksi. Beban-beban berat mulai menghimpit, jika mengingat itu. Terbayang wajah sang bunda, dengan pigmen rambut yang mulai berubah warna, dan kulit keriput termakan usia. Ada kerinduan yang merobek-robek perasaanku. Apalagi kalau mendengar suaranya di telepon.
“Kamu ndak pulang to, Ndhuk?” tanyanya dengan suara parau.
“Aku ndak tau, Bu…” jawabku sedih. Yah..rasa kangen ini sudah terkubur cukup lama. Menggejolak bagai lautan bara. Aku tak tahu bagaimana cara menuangkan rasa rindu yang meraja ini. Kami terpisah ribuan kilo, puluhan kota dan samudra, dan malangnya aku tak punya daya upaya untuk bertemu beliau..
Setelah melewati Unter den Linden, bus berhenti untuk memuntahkan banyak penumpang. Kebanyakan mereka ingin berkunjung ke Brandenburger Tor, Gerbang Persatuan Jerman yang masyhur itu. Heinrich juga turun di sana. Kupandangi dia, berharap bersua kembali di kampus. Dia terlalu tampan untuk dilewatkan. Senyum terbersit di ujung bibirku. Universitas Humboldt sudah dekat. Aku harus berkunjung ke Humboldt Universitat, universitas tertua di Berlin, untuk mencari beberapa literatur.
Ada perasaan tidak enak ketika memasuki halaman kampus terkenal itu. Beberapa mahasiswa melihatku sekilas, kemudian berlalu. Tentu bukan karena kerudungku. Kurasa negeri ini cukup ramah dan bisa menerima kehadiran muslim seperti aku. Negeri ini bukan seperti Perancis yang kurang ramah terhadap hijab. Peristiwa Black September di New York beberapa tahun lalu, tak begitu berpengaruh di sini. Sebelum memasuki perpustakaan berukuran raksasa, aku mengecek dompetku untuk menunjukkan identitas. Tetapi alangkah terkejutnya ketika aku mendapati dompetku tak ada di dalam tas! Entah kenapa pikiranku langsung tertuju pada Heinrich. Ya, si tampan yang bersamaku di sepanjang perjalanan. Perasaan suudzon sudah kutepis, tetapi aku sangat yakin Heinrich pelakunya. Simpatiku menguap. Aku menghela nafas, berusaha membebaskan perasaan jengkel dan marah yang bercampur aduk. Jumlah uang di dompet itu tak seberapa, tetapi semua dokumen pentingku ada di sana. Dengan terpaksa aku pulang naik Taksi. Ongkosnya kubayar dengan uang pinjaman dari Rani, teman sekamarku yang berasal dari Padang.
“Kok bisa sih Mbak?” tanya Rani.
“Aku gak tau Ran. Tiba-tiba saja cowok bule itu sok akrab banget dan duduk di sebelahku. Mana tahu kalo ternyata dia mengincar dompetku…” kuluapkan kesalku seketika. Ini adalah Jerman, salah satu negara makmur di Eropa, tidak seperti Jakarta. Bagaimana mungkin seorang pencopet berkeliaran? Aku hampir tak percaya itu.
“Jatuh kali Mbak…”
“Gak lah Ran. Aku yakin banget. Padahal tampangku nih melarat-melarat aja..kok ada yang tega ambil dompetku yah?”
“Hmm…tampang melarat? Aku suka kalimat itu…” Rani tertawa. Aku mendengus.
“Lagian Mbak Nadia juga gak rugi-rugi amat…bisa berduaan dengan cowok cakep..” selorohnya.
“Huuh..!”
Aku semakin penasaran dengan Heinrich Schaum. Hari berikutnya, aku mencoba-coba mencari namanya di kampus. Insting detektif tiba-tiba saja muncul, dan aku mulai mencari informasi kesana kemari. Aku jadi terbayang sosok Dana Scully, agen FBI terkenal di serial X-Files . Konyolnya, aku merasa seolah-olah menjelma menjadi dia. Mulai dari petugas kebersihan hingga teman-teman semua kuinterogasi tentang nama Heinrich Schaum, tetapi nihil. Tak ada yang mengenal Heinrich Schaum. Tapi bagaimana dia tahu namaku? Siapa sebenarnya Heinrich Schaum?
***
Waktu bergulir. Pepatah bilang, waktu akan menjawab semuanya. Aku sendiri mulai lelah dengan penyelidikan konyol itu. Minggu berikutnya, Mbak Murni mengabarkan kalau proses operasi Ibu berjalan lancar. Alhamdulillah, saking senangnya aku langsung menelepon Mbak Murni. Air mataku berderai-derai mendengar suara ibu. Ah, andai saat seperti ini aku bisa menemaninya. Kerongkonganku tersumbat. Sesuatu menyesakkan dada, kemudian meledak menjadi isak tangis. Satu janji terpatri, aku akan menjadi yang terbaik seperti harapan keluargaku.
Aku menyeruput Cappuccino Cream, berusaha menenangkan pikiran di sebuah Café kecil di kawasan Kurfurstendam. Aku butuh waktu sendirian untuk hari ini. Tugas kuliah menghunjam bertubi-tubi, menambah beban tak terperikan. Bahkan rengekan Rani yang hendak ikut kuabaikan begitu saja. Yah, aku tak bolah menenggelamkan diri dalam kegundahan. Aku harus semangat. Demi Ibu. Demi adik-adikku. Dan demi almarhum Bapak.
Aku hampir menghabiskan Capuccinoku ketika seorang pria yang sangat kukenal masuk ke dalam Café bersama seorang gadis belia. Heinrich Schaum. Sudah pasti itu dia. Bagaimana mungkin aku lupa dengan wajahnya setelah kejadian itu? Ya, wajah yang tidak bosan bercokol di otakku. Alisnya yang tebal dan rahangnya yang…….Ah! Benar-benar konyol!
Aku mendekatinya dan berusaha tetap tenang. Emosi yang menggejolak segera kuredam. Aku menyapanya dengan senyum yang kupaksakan.
“Hai, masih ingat padaku?” sapaku. Pria itu terkejut. Wajah pucatnya memerah. Ia tidak menyangka aku akan berada di tempat yang sama dengannya.
“Nadia?” gumamnya.
“Sedang berjalan-jalan?” Aku berusaha berbasa-basi. Pria itu mengangguk.
“Ini adikku, Nicole…” ujar Heinrich melirik ke arah gadis belia disampingnya. Aku tersenyum sekilas. Otakku tiba-tiba tersumbat. Entah kenapa lisanku terberangus. Pesona Heinrich membius, melumpuhkan syaraf, dan menjungkirbalikkan akal sehatku. Aku takut salah. Jangan-jangan bukan dia yang mengambil dompetku.
“Oya Heinrich, darimana kamu kenal aku?” tanyaku kemudian. Heinrich tersenyum gugup.
“Kelas Sejarah..” ujarnya cepat.
“Aku tidak ikut kelas Sejarah, Heinrich…” Aku menyeringai.
“Oh, kalau begitu aku pasti salah..” kilahnya. Tatapan matanya mulai tak tenang. Situasinya menjadi kurang nyaman. Nicole, gadis muda yang duduk di samping Heinrich tak terlalu peduli.
“Salah? Hmm....” cibirku.
Sepasang bola mata Heinrich yang berwarna hazel memancarkan suatu kesan mendalam. Ia tiba-tiba menarik lenganku agak menjauh, dan mengisyaratkan adiknya agar menunggu. Dia membawaku ke sudut ruangan, dan sejenak matanya menatapku dalam-dalam. Tuhan, aku tidak suka ini. Tatapan itu meluluhlantakkan jantungku.
“Maafkan aku..” katanya. Tiba-tiba ia mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya. Dompet. Yah..dompetku yang hilang. Ia menyerahkan kembali padaku. Diantara rasa takjub, aku hanya bisa terdiam. Rasa iba bercampur kagum tiba-tiba menyeruak, meruntuhkan dinding kemarahan yang kubangun sebelumnya.
“Uangnya sudah kupakai tapi surat-suratnya lengkap. Kalau kau mau, aku akan menggantinya…” ujarnya. Aku masih terdiam. Tak tahu harus berkata apa.
“Aku mengambilnya sejak dari halte itu. Makanya aku tahu namamu dari kartu mahasiswamu. Sungguh itu pertama kali kulakukan. Makanya aku tidak bisa langsung pergi setelah ambil dompet itu, untuk mengurangi rasa bersalah. Aku imigran dari Polandia..tak ada keluarga. Aku butuh sekali uangnya untuk membayar sewa Flat-ku yang jatuh tempo. Aku tinggal bersama adikku, tapi sayang ia belum punya pekerjaan tetap. Dulunya aku bekerja jadi pramusaji di restoran di Alexanderplatz, tapi baru-baru ini aku dipecat…maafkan aku karena menyusahkanmu..”
Lima menit aku terdiam. Tenggelam dalam rasa iba dan pesona. Aku menggeleng, menepis semua imajinasi. Sama sekali tidak menyangka kalau di negeri kaya seperti ini, masih ada kisah-kisah pilu yang tak terungkap. Heinrich, seorang imigran Polandia tampan yang tak beruntung. Mengapa tak ada sutradara atau pencari bakat yang menemukan dia? Ia layak menjadi seorang model parfum. Dalam hati aku bersyukur dengan keadaanku masih bisa tinggal di asrama nyaman, dengan ranjang busa empuk, dan tentu saja tak perlu bayar!
“Orang tua kalian?” tanyaku ragu-ragu.
“Mereka bercerai. Ayahku kawin lagi , sedang ibuku mulai sakit-sakitan, kecanduan alkohol dan tinggal di Polandia. Kami menyeberang ke Jerman, berharap agar semua menjadi lebih baik..” ujar Heinrich. Sekali lagi aku terperangah. Cerita yang biasanya kutonton di film, kini hadir di hadapanku.
“Aku turut prihatin..” gumamku lirih.
“Lupakan saja. Kami baik-baik saja. Nicole akan segera bekerja. Uang di dompetmu akan kami ganti. Tuliskan saja nomor rekeningmu..” ujar Heinrich bersemangat. Kutatap sorot positif di bola matanya.
“Oh, tidak usah dipikirkan…” ujarku spontan. Tetapi dalam hati tentu saja aku berharap uangnya dikembalikan, dan kami bisa bertemu lagi di lain waktu. Paling tidak, di sebuah café yang romantis. Berdua saja.
“Kami harus pergi. Terima kasih atas bantuanmu, Nadia. Aku tetap akan kembalikan uangmu. Aku tahu di mana kau kuliah. Tapi maaf kita tidak bisa berteman. Aku harus pergi. Kamu orang baik dan punya hidup yang sempurna. Anggap kita tidak pernah bertemu Nadia..”
“Tapi…”
“Tuliskan saja nomor rekeningnya. Kumohon.” Pinta Heinrich.
Aku menggeleng.
“Uang itu untukmu, Heinrich.”bisikku lirih. Pria Polandia itu terdiam, menatapku tak percaya.
“Selamat tinggal!” Dengan gerakan cepat, Heinrich buru-buru pergi berbaur dengan para pengunjung Café yang lain, kemudian menghilang entah kemana. Aku masih mematung, berdiri di antara rasa takjubku. Kucari Nicole, ia juga telah raib ditelan bumi. Aku berusaha mengejar, tetapi sia-sia. Mereka menghilang bersama angin. Aku menahan napas, antara percaya dan tidak dengan kejadian yang barusan terjadi. Heinrich Schaum, sosok pria Polandia berambut coklat masih menari-nari di pelupuk mata. Pesonanya masih sulit dilupakan. Mimpi-mimpi indah beterbangan tak tentu arah. Lenyap tiada bekas. Pikiran buruk menyusup perlahan. Uang itu akan dibelikan narkoba! Ah, biarlah…
Aku melangkahkan kaki di sepanjang Sungai Spree dan menerbangkan fantasi ke dunia lain. Begitulah hidup. Kadang kita harus dihadapkan pilihan-pilihan sulit yang kadang memaksa kita untuk melawan nurani. Aku menghela nafas, mencoba tersenyum. Mungkin aku minoritas di negeri ini. Tapi aku bangga masih bisa mempertahankan nuraniku dalam kepungan kultur hedonis dari segala penjuru. Aku mengeluarkan dompet itu, dan mengambil semua dokumen-dokumen pentingnya. Setelah berpikir sejenak, kubuang dompet kulit itu ke dalam Sungai Spree yang mengalir lambat. Gelombang air mengombang-ambing, menghanyutkan dompet kulit menjauh. Kupandangi, sampai benar-benar tak terlihat. Biar saja Sungai Spree menghanyutkan semua kenangan. Biar wajah Heinrich larut ke dalam Sungai Spree.
“Lupakan uang itu, Heinrich. Lagipula sudah waktunya aku membeli dompet baru…” gumamku sambil tersenyum. Menjelang senja, aku meninggalkan sungai dengan kenangan-kenangan yang kubungkus rapi, dan kusimpan dalam ruang terdalam di otak. Ah, dompet….
***


 Joewhylant
Joewhylant