Musim hujan mulai tiba, milyaran tetes hujan membasahi bumi. Melepaskan dahaga tumbuhan yang kering meranggas dilumat kemarau panjang. Bulan ini sedikit sekali aku diantari surat undangan sunatan, mungkin banyak yang tak mau menggelar hajatan tanpa tamu yang datang lantaran hujan. Aku heran, mungkinkah para pawang hujan sengaja kongkalikong dengan alam?
Musim hujan kali ini juga membuat Mak Nah, janda tua sebelah rumah uring-uringan lantaran dagangan es-nya tak laku. Para ibu berbondong-bondong menjewer telinga anak-anak mereka yang kepergok membeli es pada Mak Nah, karena khawatir bila si anak akan sakit nantinya. Kontan saja janda tua itu tak terima dan menghujat mati-matian jika musim hujanlah penyebab segala jenis penyakit datang, tak ada hubungannya dengan dagangan es miliknya.
“Hujanlah yang salah!, jangan kau kira daganganku ini penyebab anakmu demam Sanik!”, bentak Mak Nah pada Uni Sanik .
Begitulah jawab Mak Nah, setiap ada ibu yang protes tentang anaknya yang sakit demam, batuk, atau hanya sekedar ingusan saja. Aku juga termasuk yang dimarahi atau di jewer. Ibu kerap pula memergokiku yang sembunyi-sembunyi menyedoti es sirop Mak Nah.
Padahal menurutku, tak ada yang salah dengan es Mak Nah. Manis dan gurih santan bercampur sirop pandan dan ditambah sedikit potongan cincau hitam. Siapa yang tak ingin mencicipinya?
Aku kenal Mak Nah, ia adalah janda tanpa anak yang baru saja ditinggal mati suaminya. Ia amat mencintai Pak Kaeh, suaminya, hingga bersumpah takkan menikah lagi. Aku heran, manapula ada yang berniat menikahi Mak Nah. Semua juga tahu jika Mak Nah sudah tua, lagipula sifatnya yang sering buat gerah tetangga itulah yang makin membuat orang enggan berurusan dengannya. Kalau tidak perkara es dan ingus, mana sudi ibu-ibu itu pergi kerumah Mak Nah.
Sejak Pak Kaeh meninggal pula, Mak Nah membuka kedai kecil dirumah panggungnya. Hanya sebuah meja dengan dua kursi rotan, kemudian beberapa toples kecil isi santan, es batu, cincau dan dua botol sirop pandan warna hijau tua.
Meskipun begitu, kedai kecil itu tetap ramai setiap saat. Pagi, siang hingga petang. Apalagi musim kemarau, sungguh ramai. Tetangga saja sampai tergoda dengan segarnya es Mak Nah, lupa kalau mereka sering menggosipi Mak Nah, lupa kalau mereka bilang tak sudi ada urusan dengan janda tua ini. Aku pun sering beli, hampir tiap hari. Tiap siang, saat udara panas-panasnya, atau sore sehabis hujan di musim hujan pula. Sungguh tak habis-habis, aku bagai kecanduan es sirop itu.
Mak Nah membenci hujan sejak Pak Kaeh meninggal. Pak Kaeh tersambar petir selagi memanen kopi di ladang. Hari itu, aku melihat Mak Nah meraung-raung berkalang tanah kuburan Pak Kaeh, bagai babi hutan yang terluka tombak pemburu. Para tetangga pun berusaha menenangkan Mak Nah, namun tangis Mak Nah makin menjadi-jadi. Hingga membuat pemakaman Pak Kaeh memakan waktu cukup lama. Sebab mak Nah hendak terjun pula ke liang lahat. Melompat tiba-tiba. “Hendak menemani Pak Kaeh”, ujarnya sesengukan.
Semenjak itu pula, Aku juga kerap mendengar Mak Nah seolah berbicara dengan Pak Kaeh setiap pagi,seperti ketika Pak Kaeh masih hidup. Bila tak diperhatikan dengan seksama, orang lain mungkin mengira kalau Pak Kaeh benar-benar masih hidup.
“Kopi lagi kah?, ah, aku lupa kau sekarang jarang minum pagi-pagi”.
“Kau takut lambungmu sakit kan. Biar kubuat teh saja ya?”.
“Jangan susah kau pikir. Kau mati pun aku tetap bisa makan. Sekarang aku jual es. Malas kalau ambil kopi di ladang. Itu pula kerjaanmu”.
“Kau jangan senang musim hujan, jualanku tak laku. Kau bilang kopi juga tak panen bila hujan kan?”.
“Sudah kubilang jangan panen kopi dulu, masih hujan”.
“Aduk yang benar, ha?...Kau lelah kah?”.
“Jangan malas-malas, bantulah kerjaku sedikit”.
Begitulah kira-kira suara Mak Nah, sebuah dialog untuk dirinya sendiri yang dirasa seperti dialog biasa dengan suaminya. Kadang aku iba, sudah pasti berat bagi Mak Nah. Tak ada lagi orang yang biasanya diajak bercerita, para tetangga menjauhinya. Bahkan bahan untuk memaki saja tak ada. Dulu waktu Pak Kaeh masih ada, kerap kudengar suara Mak Nah menggelegar-gelegar membentaki Pak Kaeh. Ada saja bahan untuk membuat mulut Mak Nah tak bisa diam. .
Musim hujan selanjutnya, orang kampung bilang semua masih seperti biasanya. Seperti biasa ketika musim hujan. Tak ada beda dan tak ada yang berubah. Acara hajatan jarang, anak-anak mulai banyak yang sakit, es sirop Mak Nah masih sama ramainya, dan jalanan kampung yang licin.
Seperti biasa, setiap pagi. Membantu ibu jemur kasur, mengambil air di sumur Bor dengan jeriken, pergi ke ladang dengan ayah. Siang hari pulang lalu beli es sirop Mak Nah.
Aku berjalan pelan, memanggul lelah tak terkira. Terbayang-bayang es sirop mak Nah yang dingin dan segar itu. Keringat sudahmembanjiri kaos abu-abu lengan panjang yang sudah kumal dan robek disana-sini. Kaos yang sudah empat tahun menemani hariku di ladang. Ayah bilang namanya “Baju Ladang”. Baju yang hanya kita gunakan untuk ke ladang. Ibu mengajariku memilih Baju Ladang. Kata Ibu, bajunya haruslah berlengan panjang agar melindungi tubuh dari sinar matahari yang membakar kulit. Selain itu, tentu saja harus yang paling jelek, yang tidak pernah dipakai untuk pergi hajatan.
Mendekati rumah Mak Nah, Aku menyadari ada yangberubah. Tak terdengar lagi teriakan kesal Mak Nah dengan para ibu, atau ocehannya dengan“Pak Kaeh”, rumah tua itu hening dan sepi. Hingga membuatku khawatir bila-bila Mak Nah hilang diculik orang atau bunuh diri.
Aku berjalan ke depan rumah, mengamati bagian depan rumah. Pintu masih terkunci tapi daun jendela tidak ditutup. Pastilah Mak Nah dirumah, pikirku. Aku berbalik ke belakang rumah, mencari pintu belakang. Letaknya disamping kandang ayam. Benar saja, pintu itu tidak dikunci dan sedikit terbuka.
“Mak Nah!?”, tak ada jawaban.
“Tak jual es kah hari ini?”, senyap.
Bau busuk tahi ayam memasuki hidung, sungguh busuk. Apa yang diberikan Mak Nah untuk pakan ayam-ayam ini?, bangakai tikus kah?, aku tak habis pikir.
Perlahan, aku menaiki tangga kecil yang terbuat dari potongan batang kayu yang di tali dan disatukan dengan bilah yang lebih kecil secara melintang. Berderit-derit, ketika aku menginjak lantai rumah panggung itu. Lantai itu sudah cukup tua, papan-papan yang menjadi alasnya pun sudah retak. Retakan yang pecah mengikuti serat papan itu sendiri.
Dari atas rumah aku bahkan dapat melihat apa saja yang ada dibawah, ayam yang lalu lalang, sandal, dan beberapa barang kecil seperti sendok dan penggulung benang yang sepertinya tak sengaja jatuh. Pastilah Mak Nah lupa mengambilnya, atau terlalu malas untuk terbungkuk-bungkuk mencarinya dibawah kolong rumah panggung yang tak cukup tinggi ini.
Belum jauh dari tangga yang baru kunaiki, aku melihat Mak Nah sedang duduk meringkuk di dekat pintu depan, tangannya memegang pisau dan beberapa potong cincau. Aku menghampirinya, kusentakkan sedikit bahunya. Dan Mak Nah hanya diam. Kuteriakkan namanya, ia tak menjawab. Tubuhnya dingin, ia tidak bernafas!
Kalut, aku berbalik dan segera berlari menuju tangga hendak memanggil Ayah. Namun, belum sampai tangga tubuhku berhenti bergerak. Membeku. Mataku terpaku pada satu titik.
Disudut ruangan aku melihat sesosok tubuh yang kelihatan dalam posisi mengaduk santan dalam toples. Memakai baju ladang dan tubuhnya dibelitkan banyak kain. Di tangan kanannya terdapat sendok kayu yang diikatkan dengan telapak tangan oleh karet gelang.
Aroma busuk kian menyeruak dengan lalat yang beterbangan disekitarnya. Kain-kain itu awalnya berwarna putih, dan telah berubah warna menjadi coklat kehitaman, dan dari sela-selanya terdapat cairan merembes bersama sesuatu berwarna putih seukuran beras. Menggeliat-geliat. Masuk kedalam toples bening berisi santan.
Aku muntah, menyembur membasahi lantai. “Pak Kaeh!!”


 YufegiDinasti
YufegiDinasti








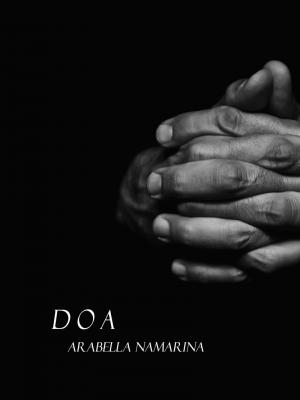

Hey,nice storyy...
Love it..., thumbs up