***
Beberapa bulan usai cekcok antara Rin dan aku, Rin putus sekolah. Konstan. Ia masih belum berubah. Malah Ia sering mengajak teman nongkrongnya ke rumah. Ibu dan Bapak menanggapinya acuh kali ini. Mereka kehabisan tenaga. Kehabisan tenaga mengurusi Rin yang sulit diatur.
Rin sering nongkrong, kelayapan malam pulang fajar. Ia juga terkadang tidak pulang ke rumah.
Kebiasaan buruk Rin membuat nama keluarga sedikit kotor di pandangan masyarakat. Orang-orang sering menggunjingnya.
Bahkan masyarakat selalu membeda-bedakan antara Rin dan aku. Aku semakin cemas. Aku tahu, Rin pasti sedang kacau sekarang.
“Rin, kamu baik-baik saja? Maafkan aku, Rin. Mari kita perbaiki bersama.” Kataku membelakanginya. Kami berada di ruang tamu, ketika hujan lebat malam itu.
Rin diam. Tidak menjawabku. Ia sepertinya tidak mendengarkanku.
Aku tidak tahu, Ia di belakangku sedang menyimpan sesuatu. Aneh. Ia menyembunyikannya dari pandanganku.
“Apa yang kamu bawa? Kok disembunyikan seperti itu, Rin?” Aku pun berbalik dengan penasaran.
“Apa sih?! Ini bukan urusanmu!” Bentaknya.
“Sudah Rin, cukup! Berhenti di sini. Aku sudah tahu sejak awal. Kamu membuat hidupmu sendiri hancur. Hidupmu kacau! Ayo kita akhiri sekarang.” Bentakku kepada Rin.
“Jangan ikut campur hidupku! Jangan sok tahu tentang jalan hidupku. Aku tidak peduli apapun katamu! Ini sudah jauh, aku terlambat untuk berhenti.” Teriak Rin, lebih terdengar seperti kalimat minta tolong di telingaku.
Tangan mulusnya itu tiba-tiba melayang di wajahku. Ia hendak menamparku, tapi seketika aku berusaha menepisnya. Menghalaunya dan melindungi diriku sendiri.
Entahlah, di waktu yang bersamaan pikiranku terbang bebas, aku hilang kontrol. Hanya suara hujan kala itu yang menjadi saksi perang kecil kami. Rasa iba ku menjadi raja di sana. Aku tidak tega, seperti luka yang belum sempat sembuh malah tertuang air garam.
Aku enggan lagi melihat belahan jiwaku kacau, aku ingin sekali menghapus perihnya.
Meskipun dengan cara...
Tiba-tiba...
***
BRAKK!! Suara hantaman tabung gitar melesat di kepala Rin malam itu.
Ia pingsan beberapa waktu...
Setelah aku pastikan, ternyata, tinggal jasad Rin di sana.
Aku segera memanggil Ibu dan Bapak, membangunkan mereka segera.
Banjir tangis di sana, Ibu terkejut. Amat terkejut.
“Ini, kenapa Ini! Kok bisa kepalanya sampai berdarah gini! Maria! Rin kenapa?” Tanya Ibu dengan menangis keras.
Aku diam seribu bahasa. Mereka sempat memaksa membawa Rin ke Rumah Sakit, akan tetapi jantung Rin sudah mendetakkan kesempatannya yang terakhir kala itu.
“Bu, Rin over dosis! Aku sudah mencegahnya, tapi dia acuh! Aku bingung, Bu! Aku takut!” Jelasku menerangkan sambil menangis.
“Apa katamu! Over dosis?! Ini kepalanya berdarah, mulutnya tidak berbusa, Maria! Mana mungkin over dosis seperti ini, Nak?!” Ibuku mencoba memastikan.
“Dia over dosis, Bu! Katanya sakit semua badannya, karena itu dia minum melebihi dosis. Maafkan aku, Bu.” Aku menguatkan.
“Kamu kan saudaranya! Pemikiranmu lebih matang dari dia. Kamu seharusnya bisa menjaganya. Kamu ini bagaimana?!” Ibu marah padaku. Tak terkendali. Ibu tenggelam.
Keesokannya, di hari pemakaman seolah bumi terpecah menjadi puluhan bagian. Lemah. Tak berdaya. Air mata membekukan suasana di sana.
BOOM!!
Di pemakaman, Bapak mengungkapkan insiden tentang kematian Rin. Aku tak sungguh tahu, bahwa ternyata Bapak semalam juga berada di sana, menguntit Rin dan aku. Dan mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya.
Seketika, suasana berubah panas. Meluap. Menatapku tajam, benci, kecewa. Terlukis di bola mata mereka, Ibu dan Bapak seperti ingin menyergapku. Aku lari jauh.
Entahlah, remote kontrolku di ambil alih.
Sial! Bapakku sudah menelepon polisi.
Ya! Terdengar tidak masuk akal, Bapak kandung menjebloskan anaknya sendiri ke penjara. Tapi, memang itu yang menimpaku.
Aku diborgol, tanganku di pegangi amat erat dan kencang higga tampak merah kulitku.
Aku takut.
***
Istana baruku, gelap, sempit, dingin, pengap. Ya, benar, tempat yang membuat semua memoriku memuntahkan isinya. Renungan. Memperbaiki diri.
Aku lunglai, terperosok amat dalam, sendiri. Hening dan sunyi.
***
Di satu sisi, aku mendapati diriku merasakan pembaruan setelah beberapa tahun melewatinya di penjara.
Tapi di sisi lain, aku adalah seorang narapidana. Namaku tercoreng.
***
Satu hal yang tak terdefinisikan. Rasa rinduku tak terbalaskan. Aku mencari-cari Ibu dan Bapak yang selama bertahun-tahun tak pernah datang membesuk meskipun sekali.
Aku pulang bersama senja, dengan aku yang baru kali ini.
“Assalamualaikum Ibu, Bapak. Maria pulang.” Wajahku sumringah.
Aku bertanya-tanya, rumah tidak di kunci, sepi. Kemana Ibu dan Bapak pergi.
“Nak, cari siapa?” Tanya seorang Bapak dari rumah sebelah, mengagetkanku.
“Maaf, Pak. Ini saya anak yang punya rumah ini. Ngomong-ngomong mereka pergi kemana ya? Biasanya jam segini mereka selalu di rumah.” Aku penasaran dengan jawaban Bapak tadi. Seingatku namanya Pak Ulil. Benar.
“Lho! Kamu belum dengar beritanya? Ibu dan Bapak kamu sudah meninggal, Nak. Dua tahun lalu. Mereka kecelakaan saat ingin membesukmu di penjara. Kecelakaan hebat itu berhasil merenggut nyawa mereka.” Terang Pak Ulil.
“Apa, Pak?! Kenapa saya baru tahu! Pihak kepolisian juga tidak memberi informasi apapun selama 8 tahun saya di penjara.” Tangisanku meluap, aku tersungkur di lantai teras rumah.
“Maaf, Nak. Bapak juga kurang tahu kalau tentang itu. Yang Bapak tahu, dua tahum lalu seorang warga yang melihat insiden kecelakaan Ibu dan Bapakmu menemukan amlpop merah muda terjatuh di sekitar TKP. Dan amplop tersebut dititipkan Bapak supaya diberikan kepadamu. Mungkin, sebelum insiden mereka ingin membesuk sekaligus menyampaikan amplop tersebut kepadamu.” Pak Ulil menyodorkan sebuah amplop merah muda kepadaku. Matanya berkunang.
Aku membaca amplop merah muda itu, seketika jiwaku menjerit kencang. Berharap ada gema yang menimpaliku.
Di dalam amplop tersebut terdapat surat, di sana tertulis permohonan maaf Ibu dan Bapak kepada Rin dan aku. Karena keteledoran mereka, Rin dan aku menjadi salah jalur dan lintasan seperti ini. Mereka amat menyesal atas hal tersebut.
Dadaku sesak, nafasku berat, mataku buram, lemas sekali rasanya membaca surat dari mereka.
Rindu...
***
Aku rindu celetukan belahan jiwaku. Aku rindu omelan Ibu. Aku rindu asap rokok Bapak. Aku rindu minum teh lemon bersama mereka.
Fatal. Aku sebatang kara sekarang.
Ketidaksengajaanku merenggut nyawa orang-orang tercintaku. Aku tak mampu. Aku tak sempat bersimpuh di lutut mereka.
Apa yang telah aku lakukan? Aku menguliti tubuhku sendiri. Menyiksa.
Tunggu aku Rin, Bu, Pak! Tunggu aku di nirwana. Ijinkan aku bersimpuh di kaki kalian. Aku bersumpah akan menemui kalian, dan menebus semua yang belum terbayar.
***
Biar waktu membeku dan aku dihakimi, dalam seperenam belas detik ini ku sulut munajat bersama apa yang tersisa di lembah hatiku.
Tiada yang mampu menembus waktu, meramal masa depan, menuntut nasib. Sebab, bukan lagi manusia yang memilih takdir, tetapi takdir yang memilih mereka. Memilih bersama siapa Ia akan terbang kemudian jatuh, terbang lagi dan jatuh lagi.
Kisah masing-masing insan, sudah terpati dan mengakar pada diri mereka.
Dalam sepertujuh belas detik berikutnya, aku akan lahir, menjadi reinkarnasi dari makhluk Tuhan yang paling sempurna. Di dunia kedua, ketiga, atau keempat...
*** END ***


 mrrrnm
mrrrnm



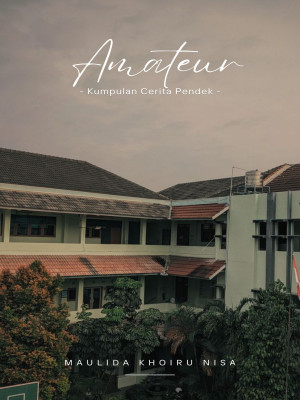

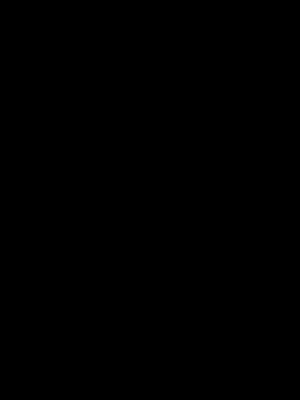







Wow mar.. Good bgt